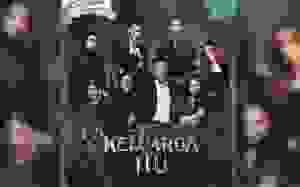Sbdj Siri 107 Makhluk Aneh Di Dusun Durian
Waktu saya dan Datuk berangkat ke Prai, nenek menghantar kami ke perhentian bas di pekan kecil. Nenek membekalkan buah tangan untuk keluarga Mat Prai, dua biji buah air serta beberapa bungkus tapai pulut.

Buat saya dan Datuk, nenek bekalkan nasi lemak. Nenek tak suka kami makan di kedai yang belum pasti kebersihannya.
"Kami naik bas dari sini sampai Taiping saja," beritahu Datuk kepada nenek.
"Dari Taiping ke Prai nak naik apa? Naik kereta api, bas atau teksi?" Nenek terus mendesak. Datuk kedutkan kening dan dahi.
"Kami nak naik teksi, biar cepat sampai ke Prai."
"Fasal berjalan, bukan main banyak duit awak," sindir nenek lalu disambut dengan ketawa oleh Datuk.
Saya cuma tumpang senyum sahaja. Alangkah bahagianya pasangan nenek dan Datuk. Walaupun sudah tua, kemesraan dan kasih sayang mereka tetap segar.
TINGGAL
Pekan kecil kami tinggalkan bersama doa restu daripada nenek. Tiga jam kemudian kami pun sampai di Prai.
Dari situ terus menuju ke rumah Mat Prai. Kami disambut dengan penuh mesra dan secara kebetulan pula, pada hari kami tiba itu Mat Prai mula mengambil cuti tahunannya selama seminggu.
"Memang tepat masanya. kami nak balik ke kampung di Balik Pulau. Sekarang musim durian. Ayah Alang boleh ikut kami. Lagipun Ayah Alang dah lama tak tengok keluarga di sini," Mat Prai yang berkulit hitam, anak jati Balik Pulau yang tinggal di Kampung Kongsi mengemukakan cadangan.
"Itu susah sikit Mat."
"Apa susahnya, semua tambang dan makan saya tanggung."
"Bukan fasal tu."
"Habis fasal apa?"
"Aku janji dengan Mak Alang kamu nak balik cepat," Datuk berdalih.
Saya agak kecewa dengan sikap yang ditunjukkan oleh Datuk itu. Kalau boleh saya mahu Datuk menurut kata Mat Prai.
Saya cukup berminat untuk pergi ke Balik Pulau. Sebuah daerah asing yang belum pernah saya jenguk.
"Tak mengapa, dia tahu kalau sudah pergi ke rumah saudara mara tentu makan masa lama. Lagipun di sana ada cerita baru," Mat Prai mula memujuk.
"Cerita apa Mat?"
"Saya dapat tahu ada cerita pelik di musim durian ni. Buah durian yang luruh malam hilang."
"Pelik apa, itu tandanya durian yang luruh dicuri orang," tingkah Datuk lalu dia ketawa berdekah-dekah.
Dari gerak geri dan air muka Mat Prai, ternyata dia kurang senang dengan ketawa yang Datuk luahkan.
Perlahan-lahan dia sandarkan tubuhnya ke dinding. Isterinya datang mengambil pinggan dan piring yang kosong.
Sebenarnya, kami baru sahaja selesai makan tengah hari. Masakan yang disediakan oleh isteri Mat Prai memang menyelerakan. Tapi Datuk makan sekadar untuk kenyang. Cuma saya sahaja yang bertambah.
"Begitulah, bila saya ceritakan semua orang ketawa, bila datang tengok dengan mata kepala sendiri, semuanya ternganga dan takut," ujar Mat Prai termengah-mengah, usia baru masuk empat puluh tahun. Ada tiga anak yang masih kecil.
Nampaknya, Mat Prai berusaha dengan sedaya upaya untuk memberikan keyakinan kepada diri Datuk.
"Saya hampa juga bila Ayah Alang tak percaya," begitu hampa nada suara Mat Prai.
Rasa kecewa terpamer di wajahnya. Sikapnya yang ditunjukkan itu menimbulkan rasa simpati pada diri Datuk.
"Kalau bukan dicuri orang, boleh jadi buah durian tu dimakan oleh harimau," kata Datuk sambil renung muka Mat Prai. Cepat-cepat Mat Prai gelengkan kepala.
"Pelik juga, kalau tak dicuri, tak dimakan harimau, makhluk apa yang membahamnya?" Datuk kerutkan kening.
"Inilah yang menjadi masalahnya, Ayah Alang."
"Banyak kebun durian orang lain yang jadi macam tu?" soal Datuk lagi.
Saya kira Datuk mula minat dengan persoalan yang disampaikan oleh Mat Prai padanya.
"Setidak-tidaknya tiga tuan punya kebun durian mengalaminya. Mereka berjaga malam. Bila terdengar bunyi durian jatuh mereka berkejar ke perdu durian. Bila sampai cuma bekas sahaja yang ada. Di tempat durian jatuh, mesti terjumpa sehelai daun sirih hutan yang tercalit kapur," Mat Prai mula membuka kisah.
"Perkara ini kau dengar cerita dari orang atau kau tengok sendiri?" Datuk mula mencungkil rahsia. Mat Prai tersenyum.
"Saya sendiri alami perkara tu, Ayah Alang!"
"Hah, kau mengalaminya sendiri?" Datuk jegilkan biji mata sambil menegakkan badannya.
Tanpa ragu dan penuh keyakinan, Mat Prai anggukkan kepala. Silanya terus diperkemaskan.
"Cuba ceritakan pengalaman kamu pada aku."
"Bila sudah terlihat daun sirih dan kapur tu, saya tercium bau kapur barus yang selalu digunakan untuk memandikan mayat. Saya juga tercium bau telur tembelang," tiba-tiba saya terasa seram dan bulu tengkuk saya terus berdiri.
Datuk menggigit bibir. Wajahnya Nampak tenang sekali.
"Kerana itulah kamu panggil aku ke mari," Datuk membuat tuduhan melulu kepada Mat Prai.
Sudah tentu Mat Prai tidak dapat menerima tuduhan itu. Secara terang-terangan dia menafikannya.
"Saya panggil bukan kerana itu, ada perkara lain yang lebih besar daripada itu. Saya kira hanya Ayah Alang sahaja yang boleh menyelesaikannya," wajah Mat Prai cukup serius.
"Apa masalahnya Mat?"
"Hubungan saya dengan adik saya bertambah jauh. Saya mahu Ayah Alang jadi orang tengah untuk mendamaikannya."
"Itu senang, kau mesti mengalah dan bertolak ansur dengannya. Walau apa pun, kau sabarlah dulu. Aku lebih berminat dengan cerita durian di Balik Pulau yang jatuh terus hilang," hati saya cukup gembira bila Datuk sudah menyatakan hasratnya secara terang-terangan kepada Mat Prai.
Saya berdoa dalam hati supaya keluarga Mat Prai berangkat segera ke Balik Pulau.
"Bila agaknya kita nak pergi?" Mat Prai pula mengajukan pertanyaan kepada Datuk.
Datuk resah. Tindakan Mat Prai membuat diri Datuk berada dalam keadaan serba salah.
"Aku ikut kamu, cepat kata kamu, cepatlah kata aku," balas Datuk.
"Apa kata selepas sembahyang Asar kita pergi."
"Boleh juga, asalkan sampai siang ke rempat tersebut. Aku nak tinjau kawasan itu. Manalah tahu boleh jadi semua itu dilakukan oleh manusia, bukan makhluk ganjil."
Datuk terus bangun. Berdiri di tepi tingkap merenung ke arah rumah para pekerja kereta api yang lain.
"Saya tak fikirkan perkara itu dilakukan oleh manusia. Ini semua kerja makhluk halus," Mat Prai bangun lalu mendekati Datuk.
Dengan tenang Datuk menggeleng kepala. Mat Prai jadi resah.
"Mesti perbuatan makhluk halus," tekan Mat Prai lagi. Datuk segera memandang ke mukanya.
"Tak boleh cakap macam tu, kita periksa dulu dan cari bukti. Manusia ni apa kurangnya dengan tipu helah," balas Datuk.
Mat Prai terdiam dan terus duduk kembali.
FERI
Petang itu, setelah menunaikan sembahyang Asar, kami segera berangkat ke jeti (sekarang Pengkalan Sultan Abdul Halim) dan dari situ menyeberangi selat kecil (saya menyebutnya sebagai Selat Pulau Pinang) dengan feri menuju ke Bandar Tanjung, (George Town – Pulau Pinang).
Kerana sudah beberapa kali datang ke bandar tersebut, tidak ada sesuatu yang menarik bagi saya.
Kami segera menuju ke perhentian bas di Pengkalan Weld untuk menanti bas ke Balik Pulau.
Mat Prai sudah memberitahu saya jalan ke sana agak bengkang-bengkok. Kalau tidak tahan boleh muntah dibuatnya.
Sebagai usaha agar saya tidak muntah dalam perjalanan, Datuk segera hulurkan secarik kertas yang disambarnya ketika kertas itu diterbangkan oleh angin di depannya.
"Buat apa tu?" tanya Mat Prai.
"Petua orang tua-tua, bila kita nak berjalan, tiba-tiba terserempak dengan daun atau kertas yang diterbangkan angin, cepat-cepat kita sambar dengan senafas. Khasiatnya boleh dijadikan tangkal penahan muntah.
"Selain dari daun dan kertas, ranting kayu boleh tak digunakan?" soal Mat Prai lagi.
"Boleh, asalkan benda-benda tu tidak terkena tanah dan datangnya dari arah matahari terbit menuju ke arah matahari jatuh," Datuk memberi penjelasan.
"Benda tu dibuat macam mana? Ditelan?" Datuk tersenyum. Pertanyaan dari isteri Mat Prai memang melucukan.
"Tak payah ditelan, cukup sekadar diletakkan di bahagian depan perut. Diselitkan pada celah seluar, kain atau tali pinggang.
"Jangan diubah-ubah atau dibuang, kecuali sampai ke tempat yang dituju. Kalau dibuang semasa dalam perjalanan, kita akan muntah dengan serta merta," dengan tenang Datuk memberikan penerangan.
"Tapi, anak saya tak muntah apabila naik bas atau kereta api," Mat Prai memberitahu Datuk tentang anak-anaknya.
"Boleh jadi kedua anak kamu tu, sudah biasa dengan jalan yang bengkang-bengkok. Cucu aku ni tak berapa biasa, jadi aku buat persediaan."
"Ya, sediakan payung sebelum hujan," tingkah isteri Mat Prai.
Datuk tersenyum dan Mat Prai terus ketawa. Bila ketawa Mat Prai berakhir dan senyum Datuk berhenti, bas ke Balik Pulau pun sampai. Tanpa membuang masa kami terus naik bas.
KONGSI
Ketika sampai di perhentian bas di pekan Kongsi yang letaknya berdepan dengan Balai Polis Balik Pulau, hari masih cerah lagi.
Kami terpaksa berjalan kaki menuju rumah arwah orang tua Mat Prai yang terletak berdekatan dengan masjid Balik Pulau.
Setelah berada lebih kurang dua jam di rumah orang tua Mat Prai, kami segera berangkat ke rumah yang didirikan oleh Mat Prai di Kampung Pondok Upih.
"Bila saya berhenti kerja, saya nak duduk di sini. Fasal itulah saya buat rumah cepat," Mat Prai beritahu Datuk.
"Bagus. Tanah ni kau beli?" soal Datuk sambil merenung kawasan rumah papan yang berbumbung lima.
"Tanah pusaka. Ini bahagian saya," jawab Mat Prai.
"Oh," Datuk anggukkan kepala.
"Besar rumah kamu," sambung Datuk. Mat Prai terus tersengih.
"Naiklah, buat apa tercegat kat situ," suara isteri Mat Prai meninggi dari tingkap dapur. Cukup pantas dia naik ke rumah lalu membuka pintu tingkap.
"Mari kita naik," susul Mat Prai.
Cakapnya itu segera kami patuhi.
Apa yang menarik perhatian saya ialah tentang karenah anak Mat Prai. Mereka cukup lincah dan riang. Berlari ke sana ke mari di halaman rumah.
Ada kalanya memanjat pepohon sekitar rumah dan membaling beburung yang terbang rendah.
Bagaikan mahu pecah anak tekak isteri Mat Prai mengingatkan mereka supaya berhati-hati bila berlari.
Jangan sampai tersepak tunggul, jangan sampai jatuh dalam longkang atau terjatuh ke dalam perigi buta.
Ingatan itu bagaikan tidak berkesan sama sekali terhadap kedua anak Mat Prai. Mereka terus berlari ke mana sahaja ikut kemahuan sendiri.
Telatah kedua orang anak Mat Prai memang membosankan tetapi, ada kalanya telatah mereka melucukan sehingga saya tersenyum panjang.
Selepas puas berlembut, akhirnya isteri Mat Prai hilang sabar apabila dia melihat anak sulungnya menebang pokok langsat.
Tanpa sebarang amaran dia terus memukul anaknya itu dengan pelepah kelapa. Datuk terpaksa campur tangan untuk meleraikannya.
"Dia, kalau dah marah memang tak sedarkan diri," bisik Mat Prai ke telinga Datuk. Nampaknya Datuk tidak dapat menerima alasan itu.
"Kamu sebagai suami harus menahannya. Kalau kau biarkan dia ikut perasaan, nanti budak yang rosak. Kamu sendiri tahu, marah tu permainan syaitan. Aku memang tak suka orang memukul anak teruk-teruk."
PERGI
Memang sudah direncanakan, selepas sembahyang Isyak dan makan malam, kami bertiga iaitu Datuk, saya dan Mat Prai akan berangkat ke tempat yang dijanjikan.
Tetapi, anehnya Datuk seperti sengaja mahu melambat-lambatkan untuk pergi ke tempat tersebut.
"Bila kita nak pergi, Ayah Alang? Kalau lambat nanti mengantuk," Mat Prai mengajukan pertanyaan.
Datuk yang tersandar di dinding segera menegakkan tubuhnya. Saya lihat kedua belah bibirnya bergerak. Dalam keadaan begini pun Datuk masih berzikir, rungut saya dalam hati.
"Tunggu sekejap," Datuk segera bangun.
Dia pergi ke telaga mengambil air sembahyang. Kembali semula ke rumah dengan wajah yang tenang. Sambil berdiri Datuk menatap wajah saya dan Mat Prai.
"Kalau boleh, biarlah muka kita sentiasa dibasahi dengan air sembahyang," secara tidak langsung Datuk mengajar saya dan Mat Prai untuk melakukan sesuatu yang baik.
Buat beberapa saat, suasana di ruang rumah terasa sepi. Saya atau Mat Prai tidak berhasrat mengajukan sebarang pertanyaan pada Datuk.
"Semua sudah siap?" satu pertanyaan yang mengejutkan dari Datuk.
Saya dan Mat Prai berpandangan. Sukar untuk saya menangkap maksud sebenar dari kata-kata Datuk itu.
"Memang dah siap nak pergi Ayah Alang."
"Kalau dah siap, mana lampu picitnya, mana penyuluhnya, mana parang panjang dan goloknya," soal Datuk dengan wajah yang serius. Saya mula memahami maksud Datuk.
"Semua sudah ada, Ayah Alang."
"Kalau sudah ada, letakkan barang-barang tu di sini, aku nak tengok."
"Tunggu, saya ambil," Mat Prai terus bangun dan keluar dari rumah menuju ke tanah.
Beberapa minit kemudian, Mat Prai datang. Semua barang yang dikehendaki oleh Datuk diletakkan di tengah ruang rumah.
Datuk menatapnya dengan senyum. Saya melihat dia melangkah ke depan dengan merendahkan badan sambil membengkokkan lutut kirinya.
Saya mula faham, langkah itu langkah berisi, ada maksud dan tujuan tertentu. Bukan langkah kosong.
"Daun kelapa untuk suluh memang banyak saya simpan," Mat Prai memberi penjelasan.
Datuk menganggukkan kepala lalu duduk mencangkung di depan barang-barang yang disediakan oleh Mat Prai. Saya kira lebih dari sepuluh detik Datuk berkeadaan demikian.
"Bukan apa-apa," Datuk melirik ke arah Mat Prai.
"Kita ni orang Melayu. Sejak zaman-berzaman menggunakan sulih atau andang bila berjalan malam. Tetapi, sekarang andang tak diperlukan. Kita sudah maju. Sudah ada lampu picit, tetapi..." Datuk tidak meneruskan kata-katanya.
Dia menarik nafas panjang sambil mengedutkan dahi.
"Kerana di kebun durian ada perkara aneh terjadi, kerana itulah aku mahu menyediakan semuanya ini," Datuk meneruskan kara-kata yang terhenti. Rasa lega bertandang dalam hati saya.
"Sekarang kita pergi," itu arahan daripada Datuk.
Serentak dengan itu Datuk terus berdiri. Saya dan Mat Prai segera mengambil barang-barang di tengah ruang dan melangkah ke pintu.
"Beri aku kepala jalan. Kau cuma beritahu nak belok ke kiri atau ke kanan," Datuk menghalang langkah Mat Prai.
Langkah saya jadi terhenti. Kesempatan itu saya gunakan untuk melihat ham dinding rumah Mat Prai.
"Dah dekat pukul sepuluh setengah,"
keluh saya dalam hati sambil melangkah dan memijak anak tangga.
Mat Prai yang mengekor di belakang tidak bersuara langsung. Bila dia sampai di halaman rumah, Datuk terus menepuk bumi dengan telapak tangannya tiga kali berturut-turut.
"Kita melangkah sekarang, tak payah pakai andang daun kelapa, memadai dengan lampu picit saja," Datuk terus berdiri di depan saya. Baru tiga kali melangkah, Datuk terus berhenti.
"Kamu di belakang aku, Si Tamar yang akhir," arahan yang tidak menggembirakan dari Datuk untuk saya.
Mat Prai segera mengambil tempatnya. Secara mendadak sahaja saya menjadi cemas dan takut.
Saya toleh ke kanan dan toleh ke kiri. Apa yang saya lihat ialah pepohon yang kaku dalam kegelapan malam. Suara cengkerik memekakkan anak telinga.
"Ayuh jalan, kau jadi tukang suluh jalan," Datuk mengingatkan Mat Prai tentang tugas yang mesti dilakukannya.
Perjalanan yang terhenti disambung kembali.
BULU
Setiap kali melangkah, saya terasa seperti ada sesuatu yang mengikuti saya. Bulu tengkuk saya meremang secara tiba-tiba.
Suara cengkerik yang tidak putus-putus itu, saya rasakan seperti tangisan bayi yang kelaparan susu.
Dalam gelap itu, saya terpandang benda putih yang bentuknya seperti batang pisang berada di awang-awangan dan sering mendekati saya.
Anehnya, bila saya jegilkan biji mata dan tumpukan perhatian ke arahnya, benda itu hilang dan apa yang saya lihat ialah dedaun dari pokok-pokok renek yang bergerak-gerak ditolak angin malam.
"Jauhkah lagi?" tanpa sabar saya mengajukan pertanyaan kepada Mat Prai.
"Dari sini kira-kira enam rantai lagi," jawab Mat Prai sambil melihat ke arah cahaya api pelita dari pondok durian milik orang setempat.
Bila dapat bercakap sambil berjalan, rasa takut dan cemas yang menguasai hati terus hilang.
Perjalanan malam yang mendebarkan itu pun berakhir. Kami sampai di pondok durian.
Mat Prai segera memperkenalkan dua budak lelaki yang berbadan tegap, berusia lingkungan 25 – 26 tahun, berkulit cerah kepada saya dan Datuk.
Kata Mat Prai, kedua-dua budak tersebut berasal dari Pulau Betung yang sengaja diupah oleh Mat Prai untuk menunggu dusun durian.
"Mereka ni memang berani, ada sedikit-sedikit ilmu dunia. Fasal itu saya panggil mereka," bisik Mat Prai pada Datuk.
"Macam mana kau upah dia orang?" soal Datuk dengan nada suara yang perlahan.
Pada hemat Datuk, kurang manis kalau persoalkan semacam itu sampai pengetahuan mereka.
Mat Prai segera menjelaskan cara upah yang dilakukan. Mereka akan mengira secara rambang jumlah buah durian yang ada.
Kemudian buah itu dibahagi dua tetapi, orang yang diupah itu dimestikan menjaga dan membersihkan dusun durian mengikut musim perjanjian.
"Satu kerjasama yang baik, berasaskan pada kejujuran dan keikhlasan," puji Datuk lalu duduk di bendul pondok.
Pemuda dari Pulau Bentung berdiri di sudut pondok.
"Tak apalah abang Mat Prai, kerana abang dah ada, biarlah kami balik," kata pemuda yang bermata besar.
"Kenapa begitu? Marilah kita tunggu bersama," saya cuba menahan.
"Memang sudah begitu janji yang dibuat. Kalau abang Mat Prai ada, kami mesti balik. Kalau dia tak ada kami ambil alih tempatnya," tingkah pemuda yang seorang lagi.
Bulu matanya cukup tebal. Apabila kedua pemuda itu mahu meninggalkan pondok durian, Mat Prai segera bertanya.
"Ada benda-benda pelik?"
"Abang tengok sendirilah," jawab mereka serentak kalu beredar meninggalkan kami.
Angin malam yang bertiup tenang membuat saya cepat mengantuk. Tanpa membuang masa saya terus merebahkan badan di lantai pondok.
Mat Prai terus menghitung buah durian di kaki tangga yang dikumpulkan oleh kedua pemuda tadi.
Datuk pula memeriksa kawasan sekitar pondok dan akhirnya berlabuh di perigi.
Saya terkejut bila Datuk mandi malam kerana perbuatan mandi malam memang jarang dilakukannya.
Mungkin Datuk mempunyai maksud dan tujuan tertentu, fikir saya sambil menggolekkan tubuh ke kiri dan ke kanan lantai pondok yang dibuat daripada bulu.
"Tolong saya, Ayah Alang. Tolongggg..."
Saya terkejut dan segera bangun bila mendengar jeritan Mat Prai. Serentak dengan itu secara tiba-tiba lampu minyak tanah yang tersangkut pada tiang pokok terus padam.
Kulit durian berterbangan ke arah saya. Badan saya terasa pedih dan luka. Saya terpaksa merangkak dalam gelap.
Jeritan Mat Prai tidak kedengaran lagi. Dia mengerang macam orang menahan sakit yang amat sangat.
Saya terus memanggil nama Datuk beberapa kali. Malangnya, laungan itu dihalang oleh bunyi air yang jatuh ke tubuh Datuk.
Dalam keadaan yang tidak menentu itu, terdengar bunyi paluan kompang yang disertai dengan sorak-sorai yang meninggi.
Saya terus merangkak dan meraba dalam gelap. Entah macam mana saya terlanggar dinding pondok yang dibuat dari tepas.
Dinding itu terkopak dan saya terdorong ke depan lalu jatuh ke tanah macam nangka masak yang lekang daripada tangkainya. Sakitnya bukan kepalang.
Walaupun sakit, saya cuba bangun dengan berpaut pada tiang pondok. Usaha itu tidak berhasil. Saya tidak dapat bergerak ke mana-mana kerana gelap.
Saya terus memeluk tiang pondok. Entah macam mana saya terasa seperti ada makhluk ganjil yang muncul di sisi saya.
Dalam keadaan yang cemas itu, leher saya diraba oleh sepasang tangan yang berbulu tebal dan panjang.
Tangan berbulu itu bergerak dari batang leher ke muka lalu menyentuh pipi, hidung dan mata.
Bila telapak tangan berbulu berada di atas lubang hidung membuat saya sukar bernafas. Tanpa diduga tubuh saya dipeluk dengan eratnya.
Dengan sedaya upaya saya cuba meronta, entah macam mana kaki saya tersepakkan sebatang kayu.
RENDAH
Saya pun merendahkan badan lalu mengambil kayu tersebut. Dengan sepenuh tenaga, hujung kayu itu saya hentakkan ke tubuh berbulu.
Dalam gelap itu saya terdengar suara orang mengeluh menahan kesakitan yang amat sangat.
Serentak dengan itu, sepasang tangan yang berbulu yang memeluk tubuh saya beransur lemah dan akhirnya saya bebas dari pelukan yang membuatkan saya sukar bernafas.
Saya terus merangkak dalam gelap tanpa matlamat yang tertentu. Kepala lutut saya terasa pedih bila terlanggar kulit durian. Entah macamana saya terpeluk tubuh Mat Prai.
"Siapa?" tanya Mat Prai.
"Saya, lampu picit di mana?" soal saya sambil duduk dalam gelap.
Mat Prai bercakap sendiri menyalahkan dirinya kerana meletakkan lampu picit merata-rata.
"Aku ingat, aku letakkan dekat tunggul merbau di sebelah kanan pondok. Apa yang mesti kita buat, Tamar?"
"Kita terpaksa cari."
"Terpaksa merangkak dalam gelap? Ini kerja susah," Mat Prai seperti berputus asa.
"Kita tak ada jalan lain, kita mesti cari lampu picit," kata saya dan terus merangkak.
Angin malam yang bertiup membuat dedaun bergeselan sesama sendiri.
Bunyinya tidak menentu, ada ketikanya seperti daun kereta api dan di masa yang lain pula bunyinya macam bunyi ombak laut.
Serentak dengan itu saya terdengar bunyi burung jampuk. Awan di langit kelihatan hitam pekat.
Nyanyian cengkerik bertingkah dengan suara katak. Lolongan anjing liar di pinggir pekan Kongsi jelas kedengaran.
Bulu roma saya terus berdiri. Tidak terdaya rasanya mahu merangkak. Dari setiap sudut saya terdengar suara orang ketawa dan menangis.
Tamat Siri Bercakap Dengan Jin 107/284
BACA: SBDJ Siri 106: Harimau Sembunyi Kuku
BACA: Siri Bercakap Dengan Jin (Koleksi Lengkap)
-Sentiasapanas.com
Artikel ini hanyalah simpanan cache dari url asal penulis yang berkebarangkalian sudah terlalu lama atau sudah dibuang :
http://www.sentiasapanas.com/2019/09/siri-bercakap-dengan-jin-107.html
 PING BABAB : Raksasa Aggregator Malaysia
PING BABAB : Raksasa Aggregator Malaysia