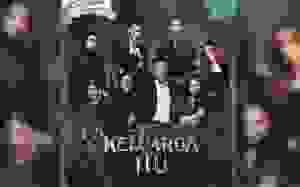Masyarakat Yang Malas Berfikir Otak Pajak Pada Orang Lain
Masyarakat yang malas berfikir
Faisal Tehrani -May 12, 2022 Baru-baru ini saya menciap satu status perihal Melayu yang ‘malas’ berfikir, dan mungkin juga datang dari kemalasan serba-serbi. Tentu saya menciapnya berdasarkan konteks dan sebagai pengikut Syed Husein Alatas dan Jose Rizal, saya cukup mengerti ehwal mitos peribumi malas. Seorang pengarang berwibawa, Wan Nor Azriq nampaknya tidak bersetuju dengan saya dan mengulang ciap dengan kata-kata; “Kalau penulis pun hilang kepercayaan pada masyarakatnya sendiri, maka apa bezanya seorang penulis dengan para politikus angkuh yang sentiasa menindas masyarakat?”.
Oleh kerana ciapan beliau itu memesongkan makna yang ingin saya hantar, dan oleh sebab beliau sangat popular berbanding saya; maka saya khuatir status itu akan membawa salah erti yang berpanjangan.
Saya ingin menjelaskan perihal “penulis pun hilang kepercayaan pada masyarakatnya sendiri” itu di sini. Sebagai pengarang lama, saya sudah menulis lebih 30 tahun, sudah dapat dianggap pengarang tua tanpa pengikut berbanding Azriq. Itu jugalah sebabnya saya risau jika status perihal Melayu yang malas berfikir itu diselewengkan maksudnya.
Saya bimbang jika pengarang atau penulis disaran untuk tidak mengkritik dan menasihati masyarakatnya. Ini satu mesej yang salah dan lalai kerana kerja penulis bukan sekadar bercerita yang “absurd-absurd” saja.
Sebenarnya, kerja pengarang dan pemikir itu memang memesan-mesan kepada masyarakatnya, dan mereka dibenarkan untuk hilang kepercayaan pada masyarakat sendiri. Saya pernah membaca dan menulis mengenai Prof Ungku Aziz yang menukil dalam sebuah artikel pendek berjudul Tragedi Pemikiran Melayu, yang mana beliau mencatat begini:
“Saya rasa Melayu tidak sanggup berubah; perspektif mereka terhad, tidak suka menyiasat dan mereka tidak mahu berfikir dengan mendalam.”
Tulisan saya itu terbit di kolum ini dengan judul Melayu Pandai Buat Bakul. Tentulah Ungku Aziz itu mengkritik Melayu dan saya tak tahu jika ayat di atas menunjukkan beliau ada kepercayaan kepada bangsa Melayu. Saya percaya kata-kata pedas itu digunakan untuk menyentak pembaca.
Jikalau kita membaca macam-macam karya sasterawan negara, ada macam-macam kritikan terhadap bangsa Melayu. Itu pun belum tentu mereka sebetulnya hilang kepercayaan. Za’ba, Burhanuddin Al Helmy, dan Shahnon Ahmad semuanya menegur perangai bangsa Melayu tanpa penat lelah. Mana yang tak elok kita pengarang cuba elokkan (meskipun kita belum mesti sempurna dan elok semua). Seperti mereka, saya berhak menegur bangsa saya sendiri. Kalau tidak Dr Mahathir Mohamad mengatakan Melayu itu malas pun kita akan temukan banyak tulisan pemikir bangsa yang menegur malasnya Melayu untuk berfikir.
Perihal “penulis pun hilang kepercayaan pada masyarakatnya sendiri” yang disebut itu misalnya terkandung dalam sebuah buku bertajuk Renongan: Antoloji Esei Melayu Dalam Tahun 1924-1941 terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka pada 1964, susunan Zabedah Awang Ngah. Saya ingin membujuk pengarang muda yang pandai-pandai di luar sana, tekunilah minda orang terdahulu. Kenapa saya ingin menghujahkan dengan buku lama ini? Kerana pertama, saya ingin membuktikan memang ramai pemikir, pengarang, dan budayawan Melayu yang sejak sekian lama sudah mengkritik dan hilang kepercayaan pada masyarakatnya sendiri.
Kedua, pemikir, pengarang dan budayawan Melayu yang mengkritik dan hilang kepercayaan pada masyarakatnya sendiri itu sudah melakukannya sejak 1930-an, sebelum Perang Dunia lagi. Ketiga, saya risau kalau generasi pengarang selepas saya mempersetankan pengarang generasi lama seperti Pak Sako, Za’ba dan lain-lain serta mengagungkan pengarang luar yang menulis hal-hal “absurd”. Padahal orang seperti Pak Sako itu pemula dan berhak dipuja.
Keempat, pengarang dalam buku Renongan ini bukan mamak Kutty, bukan kacuk Turki seperti Ungku Aziz, bukan Arab celup tetapi Melayu asli. Mungkin dalam kalangan mereka ada yang Jawa, Bugis, Banjar atau Minang; tetapi mereka Melayu. Salah seorang yang tulisannya amat pedas pada 1941 di majalah Guru malah seorang ‘Wan’, berbanding saya yang tiada Syed, Meor, atau Wan.
Dalam buku Renongan: Antoloji Esei Melayu Dalam Tahun 1924-1941, penyusun yang menyunting esei-esei cikgu sekolah Melayu zaman sebelum perang merakamkan betapa karangan mereka itu nampaknya meminjam ungkapan Azriq, ‘hilang kepercayaan pada masyarakat sendiri’. Catatan Zabedah mengenai tulisan mereka itu begini;
“Sikap penulis-penulis esei terhadap faktor-faktor keburukan dalam masyarakat ini timbul dengan perasaan-perasaan benci, cemas dan tidak bertolak-ansur. Mereka menggunakan senjata-senjata mereka untuk menyelar pendukung-pendukung penyakit-penyakit masyarakat itu dengan kata-kata yang pedas seperti perkataan-perkataan ‘bodoh’, ‘buta kayu’, ‘pemalas’, dan sebagainya.”
Dalam erti kata lain, pengarang sebelum Perang Dunia Kedua sudah memanggil bangsa sendiri “bodoh”, “buta kayu”, dan “pemalas”. Tentu dengan tujuan menegur dan menasihat. Tentu juga tidak sama bangsa Melayu sendiri yang memanggil Melayu itu “bodoh”, “buta kayu”, atau “pemalas”. Mereka bukan mendendangkan naratif penjajah tetapi menulis berdasarkan pemerhatian.
Omar Kaya dalam Majalah Guru keluaran April 1925 memanggil Melayu “tidak amanah” dan itu menurut kata beliau menjadi “sebab-sebab kejatuhan dan keciciran kaum kita ke belakang”. M Zai dalam Tetauan Muda pada Jun 1927 mengatakan Melayu itu kaki “menipu” dan “selalu ada kesilapannya oleh kerana jahil mereka”. A Bakariah dalam Majalah Guru edisi Ogos 1933 pula menyatakan Melayu itu “menaruh hati yang hasad dan dengki”. ZBS (nama pena) dalam Majalah Guru keluaran Januari 1940 pula menyatakan orang Melayu itu ada niat untuk bekerja, tetapi ujar beliau “benih bekerja itu tidak bersemangat”.
Rentaka Melayu dalam majalah Guru pada Oktober 1937 mengatakan Melayu di kampung itu tidak peduli dengan masalah negara; “perhatikanlah bagaimana keadaan kaum kita yang di kampung-kampung: mengertikah mereka apa yang dikatakan politik, ekonomi, ‘Malayan’, kebangsaan, dan lain alat kemajuan bangsa-bangsa sekarang?”
Agak-agaknya apa yang disebut Rentaka Melayu itu masih berlaku dalam kalangan orang Melayu kita atau tidak?
Al Ikhwan dalam editorial Disember 1929 pula menegur bangsa Melayu yang menadah saja khutbah para agamawan tanpa mengerti apa-apa:
“…bilakah satu kali Nabi Muhammad yang membawa agama Islam ini ada pernah membaca pada hari Jumaat itu dengan bahasa yang dia sendiri tidak mengerti apa yang dibacanya itu, dan bilakah pernah Nabi Muhammad itu berkata-kata dihadapan orang ramai pada hari Jumaat itu dengan bahasa yang orang itu tidak mengerti apa yang dikatanya.”
Wan Ismail Abu Bakar dalam Majalah Guru September 1941 pula nampak kesal dengan anak muda Melayu yang hanya berfikir untuk makan gaji dan tidak “meniru contoh teladan orang Cina”. Wan Ismail malah secara berbisa mengecam anak muda yang malas ini sebagai “kalau tak kuasa hendak kerja masuk bersarang di rumah sakit lah.”
Nabi-nabi yang didatangkan oleh Yang Maha Esa kepada kaumnya, memang hilang kepercayaan pada masyarakatnya sendiri. Kalau tidak, tidaklah Nabi Nuh itu hidup beribu tahun menyeru kepada kebaikan dan dipukul sehingga pengsan setiap tiga hari sekali. Kalau tidak, tidaklah Nabi Zakaria itu digergaji. Kita tahu bila Nabi Muhammad hilang kepercayaan terhadap masyarakat Quraisy dan menegur mereka, baginda bahkan dipanggil gila, ahli sihir, dan orang sasau semata-mata kerana Rasulullah bercakap yang betul tentang perangai orang Quraisy yang tersinggung lantaran ditegur.
Hujah bahawa kita tidak boleh menegur orang Melayu ini ialah hujah golongan ekstrem, yang ingin sedap berbuat apa sahaja. Kalau kita berhenti menegur mereka, maka sedaplah mereka menyauk. Lagi kita menulis yang “absurd-absurd”, lagi habis mereka menyauk. Persis hujah Quraisy yang enggan berubah dan melakukan reformasi. Mereka takut tidak boleh lagi mencabul kehormatan perempuan, tidak boleh lagi menghambakan manusia lain, tidak boleh lagi menjarah harta taulan, tidak boleh itu dan ini. Bila ditegur, maka beramai-ramai melenting. Akhir-akhir Nabi Muhammad diharamkan, dan terpaksa mengungsi.
Saya bimbang dengan pandangan Azriq dan pengikutnya yang sangat ramai itu; yang menyangkakan penulis tidak boleh hilang kepercayaan pada masyarakat saya sendiri, yang membawa isyarat penulis usah mengkritik bangsa ini (meskipun mereka mencintai korupsi). Sebagai pengarang lama, saya sudah menulis lebih 30 tahun, sudah dapat dianggap pengarang tua tanpa pembaca berbanding Azriq, itu jugalah sebabnya saya risau jika status perihal Melayu yang malas berfikir itu diselewengkan maksudnya.
Azriq sebagai satu kebalikan memiliki ramai pengikut, dan orang yang hebat; saya cuma khuatir nanti ramai yang percaya bahawa jangan ditegur orang Melayu kalau mereka berbuat tidak senonoh. Manakala kita alpa itu ada penyangak sedap menyauk.
Saya merayu penulis muda untuk membaca karya-karya generasi terdahulu dan celik mata oleh kebobrokan bangsa kita. Buku Renongan yang saya jadikan contoh di atas itu hanyalah satu contoh kecil. Untuk berubah kita perlu, kata orang Arab; bermuhasabah.
Akan tetapi kalau menegur pun dilarang, tidakkah itu tanda betapa malasnya kita untuk berfikir?
Artikel ini adalah pandangan penulis dan tidak semestinya mewakili FMT.
Artikel ini hanyalah simpanan cache dari url asal penulis yang berkebarangkalian sudah terlalu lama atau sudah dibuang :
https://wrlr.blogspot.com/2022/05/masyarakat-yang-malas-berfikir-otak.html
 PING BABAB : Raksasa Aggregator Malaysia
PING BABAB : Raksasa Aggregator Malaysia