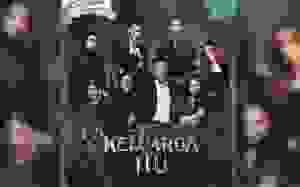Kenangan Membesar Di Rumah Tengah Sawah Padi

Kenangan Semasa Dibesarkan di Rumah Tengah Sawah Padi pada Tahun 70an
Oleh: Abe Kie
Tahun 1970an. Dunia waktu itu tidak bergantung pada gajet, tiada talian internet, tiada siaran televisyen 24 jam. Namun, bagi seorang budak kampung seperti aku, dunia itu penuh warna dan cerita. Aku dibesarkan di sebuah rumah kayu beratapkan rumbia, terletak betul-betul di tengah-tengah sawah padi yang luas terbentang di daerah Machang, Kelantan.
Rumah itu bukanlah besar. Bilik cuma tiga, dinding dari papan berwarna kusam, lantai dari kayu cengal yang sejuk bila dinihari. Dapurnya di belakang, sedikit tinggi dari tanah, berlantaikan buluh yang berkeriut setiap kali emak memijaknya. Tapi rumah itu syurga kami — tempat segalanya bermula.
Ayahku, Pak Din, seorang petani tulen. Kulitnya gelap terbakar, tangannya penuh calar dan kapalan. Walaupun kerja sawah itu berat, tak pernah sekali pun aku dengar dia mengeluh. Setiap pagi sebelum subuh, dia sudah bangun, bersarung kain pelikat dan berbaju pagoda putih yang sudah luntur warnanya, bersiap dengan cangkul dan sabit. Kadang-kadang, aku yang ketika itu berumur enam tahun, ikut turun ke sawah selepas waktu subuh, berkaki ayam menapak batas yang lembik.
"Jangan pijak padi tu, Kie," kata ayah suatu pagi, sambil memandang aku dengan senyum. "Itu rezeki kita. Jaga elok-elok."
Aku angguk, meski belum faham sepenuhnya apa yang dimaksudkannya dengan ‘rezeki’. Yang aku tahu, sawah itu tempat ayah mencari makan, dan tempat kami bermain-main bila musim tidak sibuk.
Emak pula, orangnya lembut tapi tegas. Namanya Masamah. Tangannya cekap membuat segala jenis kerja rumah — dari memasak hingga menjahit baju sekolah kami. Kadang-kadang dia ke bendang juga, terutama waktu menanam dan menuai. Tapi di rumah, dialah ratu. Waktu pagi, selepas memasak nasi di dapur kayu, dia akan panggil kami bersarapan — biasanya dengan gulai ikan kering, sambal belacan, dan ulam pucuk ubi yang dipetik sendiri dari tepi batas.
Kami lima beradik. Aku anak yang kelima. Kakak sulungku, Maizun, sudah habis sekolah menengah waktu itu. Seringkali dia yang mengangkat air dari perigi belakang rumah dan tolong ayah membaiki atap atau membina rak kayu di bawah rumah untuk menyimpan guni padi. Dua orang lagi kakakku Normadiah dan Hasnah sering membantu ibuku melakukan kerja-kerja rumah manakala abangku, Kamaruzaman sering membantu ayah membuat kerja-kerja ringan seperti menambat kambing dan lembu di padang yang terbentang luas.
Waktu petang, selepas kerja bendang selesai, ayah akan duduk di anjung rumah sambil menghisap rokok daun. Kami pula, anak-anak, akan berlari ke sungai kecil di hujung sawah untuk mandi. Airnya jernih, sejuk menggigit kulit, dan di dasar ada batu-batu halus serta ikan puyu yang kadang-kadang melintas deras di celah kaki kami. Kami mandi berjam-jam, hinggalah emak datang memanggil dengan suara lantang.
“Oi, dah senja! Cepat naik, nanti kena demam!”
Malam di rumah sawah itu tak pernah sunyi. Di sekeliling rumah, cengkerik berbunyi, sesekali bunyi katak dan burung hantu bersahutan. Lampu gasolin yang tergantung di ruang tamu memancarkan cahaya kekuningan. Kami akan duduk bersila di atas tikar mengkuang, mendengar cerita dongeng dari emak atau cerita zaman darurat dari ayah — tentang bagaimana mereka lari bersembunyi di dalam semak sewaktu komunis menyerang kampung pada awal 50an.
“Zaman dulu, nak makan pun susah. Nak tengok nasi pun belum tentu. Sekarang, syukur kita dapat makan tiap hari,” kata ayah sambil menghembus asap rokok ke udara.
Aku mendengar dengan mata terbeliak, penuh rasa ingin tahu. Di luar rumah, kunang-kunang menari di tengah gelap malam, bagai lampu kecil dari alam lain.
Musim menuai adalah yang paling kami nantikan. Kampung jadi meriah. Sanak saudara dari kampung sebelah datang membantu. Suasana seperti pesta. Bau jerami segar, suara orang ketawa, dan jeritan kanak-kanak bermain di celah guni padi mewarnai hari-hari kami. Kadang-kadang emak masak nasi kawah, lauk gulai daging dan sambal tumis ikan bilis. Semua makan bersama, duduk bersila atas tikar mengkuang di bawah rumah.
Ada juga waktu-waktu sukar. Pernah satu musim, banjir melanda. Air naik hingga paras lutut. Kami terpaksa naik ke loteng, dan bekalan makanan disimpan dalam tempurung kelapa yang terapung. Tapi anehnya, waktu itu kami tetap ketawa. Ayah buat rakit dari batang pisang, dan kami adik-beradik duduk atasnya sambil menyanyi lagu rakyat.
Hari ini, bila aku menjejak kaki ke tapak rumah lama itu, tiada lagi sawah padi. Segalanya sudah menjadi deretan rumah batu dan jalan tar. Rumah kami sudah lama roboh. Namun dalam ingatan ini, setiap sudut rumah masih hidup. Bau kayu tua, bunyi gergaji ayah di petang hari, suara emak memanggil dari dapur — semuanya masih segar.
Anak-anakku hari ini hidup dalam dunia yang serba moden. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya tidur di bawah kelambu sambil ditemani bunyi cengkerik. Mereka tidak tahu manisnya makan nasi panas berlauk ikan sepat kering hasil tangkapan sendiri. Tapi aku harap, satu hari nanti, mereka akan baca catatan ini, dan tahu — bahawa di tengah-tengah sawah padi suatu ketika dahulu, pernah wujud sebuah dunia yang penuh kasih sayang, perjuangan, dan ketulusan hidup.
www.zukidin.com {Estd 2012}
Artikel ini hanyalah simpanan cache dari url asal penulis yang berkebarangkalian sudah terlalu lama atau sudah dibuang :
http://www.zukidin.com/2025/08/kenangan-membesar-di-rumah-tengah-sawah.html
 PING BABAB : Raksasa Aggregator Malaysia
PING BABAB : Raksasa Aggregator Malaysia