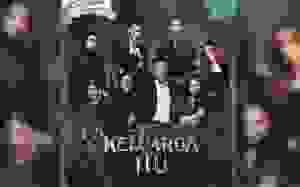Sbdj Siri 55 Mamat Bukit Yang Gagah
Saya dan Datuk berpandangan, tahulah kami sebelum kami tiba ke situ, mereka terlebih dahulu sampai. "Lagi apa yang kau dapat?", tanya Mamat Bukit pada Dollah Beranggas sambil merenung muka Samad Perang.

Mereka berbalas senyum. Dengan tenang Dollah Beranggas mengeluarkan seluar dan baju kelabu yang ada tanda tentera di dadanya. Dia juga mengeluarkan beberapa kerongsong peluru.
"Ini baju dan seluar dalam perempuan. Aku jumpa tiga keping gambar”, Dollah memberikan gambar-gambar itu pada Datuk.
Habis saja Datuk melihatnya diserahkan pada saya.
Saya lihat gambar itu dengan tenang, dua keping gambar menunjukkan dua orang lelaki bersama keluarganya, manakala yang sekeping lagi gambar seorang gadis bersama orang tuanya. Saya kira lelaki tua itu ayahnya.
"Saya fikir barang-barang ni membahayakan diri kita. Kalau kita tertembung dengan orang dalam (komunis) kita akan ditahan dan kita tak boleh mencari rotan di sini”, ujar Mamat Bukit.
"Apa yang nak ditakutkan? Kita jumpa dari bangkai kapal terbang. Orang dalam tu sendiri tentu sudah jumpa lebih dahulu dari kita. Aku ingat orang-orang yang ada di dalamnya sudah dibunuh”, Dollah Beranggas bersuara.
Dia terus memberitahu Datuk yang dia dan kawan-kawannya pernah melihat sebuah kapal terbang berlegar-legar rendah di kawasan hutan Bubu, Senggeng, kemudian terus hilang.
"Aku melihatnya dari Kampung Cangkat pada satu petang kira-kira tiga bulan yang lalu, dan sekarang kita sudah jumpa”, tambah Dollah Beranggas lagi.
Dia enggan memenuhi permintaan Mamat Bukit yang mahu semua barang-barang itu dibakar.
"Demi keselamatan diri kita, ada baiknya kita bakar”, kata Datuk.
Dan cakap Datuk itu segera dipatuhi. Selepas menunaikan sembahyang Maghrib, semua barang-barang itu jadi bahan unggun api.
Rasa sedih dan hampa terbayang di wajah Samad Perang dan Dollah Beranggas.
Kira-kira dua belas malam, bangsal tempat kami berteduh bergegar, macam digoncang orang.
Datuk yang sedang wirid membaling tasbih segera membangunkan Mamat Bukit dan Mamat Bukit memerintahkan kawan-kawannya memeriksa setiap penjuru bangsal.
Tidak terdapat tanda-tanda kesan orang atau binatang liar yang datang ke situ. Keadaan begini mendatangkan rasa cemas di hati saya.
"Tiga batang rotan semambu saya hilang”, Datuk mengadu kepada Mamat Bukit yang masih tercegat di depan bangsal. Wajah Mamat Bukit saya lihat cemas sedikit.
"Di mana awak letak?"
"Saya letak dekat hujung lutut."
"Awak dah cari?"
"Nak cari apa, masa bangsal ni bergoyang rotan semambu masih ada lagi di situ tak sampai seminit rotan semambu itu hilang dari mata.
Mamat Bukit terdiam mendengar penjelasan dari Datuk.
Dengan lampu picit berubat (bateri) lapan, Mamat Bukit menyuluh tempat Datuk meletakkan rotan semambunya.
Datuk menepuk dahi dua tiga kali, rotan semambunya masih berada di situ. Bila Datuk mahu menjamahnya, Mamat Bukit segera menahannya.
“Jangan, kita tengok dulu”, kata Mamat Bukit tanpa mengubah pancaran cahaya lampu picit nya.
Tiga batang rotan semambu itu bergerak-gerak dan bertukar warna dari hijau menjadi merah, hitam dan kuning macam tembaga.
Dalam beberapa saat pula bertukar menjadi ular tedung yang kepalanya menghala pada kami.
Mamat Bukit terus melompat dan menyambar ranting pokok berdaun hijau di sisinya.
Daun dan ranting dihumbankan pada rotan semambu yang menjadi ular.
Ketika ranting dan daun hijau mengenai rotan semambu, saya terlihat satu pancaran cahaya macam kilat yang datang dari arah kanan bangsal, rotan semambu milik Datuk kembali pada keadaan asalnya.
“Ganjil”, kata Datuk.
"Ganjil pada awak, pada kami tidak. Hal semacam itu selalu terjadi pada pencari rotan”, dedah Mamat Bukit lalu mengajak saya dan Datuk duduk berlonggok dengan kawan-kawannya.
"Kalau awak nak tahu itulah penunggu rotan”, tiba-tiba Udin Candung bersuara.
Kata-kata itu ditujukan pada Datuk.
"Itu syaitan”, balas Datuk.
"Bukan. Itu penunggu”, sahut kawan-kawan Mamat Bukit serentak.
Mereka seolah-olah tidak mahu menerima dengan apa yang diucapkan oleh Datuk.
Saya lihat Datuk tersenyum. Dia tidak marah bila orang tidak mahu menerima pendapatnya.
Kerana takut berlaku sesuatu perkara yang tidak diingini terjadi, satu keputusan telah diambil.
Semua yang ada di situ tidak boleh tidur serentak.
Datuk terkecuali dari keputusan itu kerana dia sudah pun tidur selepas menunaikan sembahyang Isyak, kira-kira dua jam lamanya.
Sekarang, Datuk memutuskan untuk berjaga sampai pagi sambil membaca ayat-ayat suci.
"Awak boleh pilih sama ada mahu berjaga atau tidur”, kata Mamat Bukit pada saya sambil tersenyum.
Kerana memikirkan berjaga lebih selamat dari tidur, saya memutuskan untuk berjaga macam Datuk.
Ternyata Mamat Bukit senang dengan keputusan itu.
"Kau orang tidur dulu, biar aku sama Dollah Beranggas berjaga. Bila aku kejut kau orang mesti bangun”, beritahu Mamat Bukit pada Udin Candung dan Samad Perang.
Tidak ada bantahan daripada orang yang menerima arahan. Udin Candung dan Samad Perang pun merebahkan badan masingmasing.
Sudah setengah jam masa berlalu. Dollah Beranggas tidak mampu berjaga. Atas rasa kasihan Mamat Bukit mengizinkan Dollah Berangas tidur.
Tinggallah saya dan Mamat Bukit menghadapi unggun api.
Datuk tidak menghiraukan kami, dia tetap dengan tugasnya membilang tasbih dan membaca ayat-ayat suci dalam bangsal.
Saya terhibur dengan cerita-cerita yang diungkapkan oleh Mamat Bukit tentang pengalaman-pengalaman aneh yang dialaminya ketika bermalam dalam hutan.
Semua cubaan dan rintangan itu dapat diatasinya.
Berdasarkan pada cerita-cerita itu, saya segera membuat kesimpulan bahawa Mamat Bukit bukanlah calang-calang orangnya.
Menurutnya, gelaran Bukit di hujung namanya itu diberi oleh penduduk-penduduk kampungnya kerana kepandaiannya menguasai puncak bukit serta tahu nama-nama bukit di daerahnya.
Memang seronok bercakap atau berborak dengan Mamat Bukit, masa yang berlalu tidak terasa sama sekali.
"Cahaya”, jerit saya bila melihat cahaya api itu datangnya dari salah satu puncak gunung dari barisan Banjaran Titiwangsa.
Saya perhatikan cahaya itu menuju ke arah kami.
"Bertenang”, bisik Mamat Bukit pada saya.
Mamat Bukit pun bangun. Berdiri sambil merenung tajam ke arah cahaya itu. Dia meluruskan tangan kanannya ke arah cahaya itu.
Kelima-lima jarinya terkembang macam menahan sesuatu. Dalam beberapa detik kelima-lima jarinya bergerak macam orang memulas buah kelapa.
"Puhhhhhh...”, katanya sekuat hati.
Saya lihat cahaya sebesar bola tenis bagaikan pecah, berserakan di udara dan akhirnya hilang entah ke mana.
Dahi Mamat Bukit berpeluh dan dia terus jatuh. Dalam beberapa minit saja dia bangun kembali.
Mungkin kerana kedinginan dia terus merapatkan badannya ke unggun api. Datuk masih lagi dengan tugasnya.
Dengkur kawan-kawan yang tidur bertambah kuat. Lagi sekali saya terkejut, apabila seekor lembu jantan berwarna putih berdiri di sebelah kanan Mamat Bukit, sambil ekornya memukul badannya.
Bila Mamat Bukit bergerak, lembu itu dengan tiba-tiba bersuara, jadi marah dan merenung ke arah saya dan Mamat Bukit.
Belum pun sempat saya dan Mamat Bukit berbuat sesuatu, lembu itu terus mengelilingi unggun api beberapa kali.
Akhirnya, lembu itu naik minyak dan menyerang apa saja yang terdapat di sekelilingnya. Dua tiga kali lembu itu mahu melanggar saya.
Kalau tidak kerana kecekapan Mamat Bukit mempertahankan diri saya dengan gerak dan langkah silatnya yang tangkas, sudah pasti badan saya hancur dipijak lembu tersebut.
"Kau ke sana”, Mamat Bukit menolak badan saya dari berpaut padanya.
Saya terdorong agak jauh juga dari unggun api. Rupanya Mamat Bukit menggunakan kepintarannya, dengan berbuat demikian lembu yang sedang naik minyak itu akan menyerang saya.
Dalam saat begitu memberi kesempatan pada Mamat Bukit melakukan sesuatu.
Ketika lembu itu memburu saya, Mamat Bukit terus menyambar ekor lembu dan terus dipulasnya dengan sekuat hati.
Mamat Bukit dan lembu memperadukan tenaga. Dalam pertarungan itu Mamat Bukit lebih hebat, lembu itu tidak terdaya menarik batang tubuh Mamat Bukit.
Lembu itu terus jatuh dan hilang, tanah tempat lembu itu jatuh berasap dan berlubang.
Seluruh badan Mamat Bukit dibasahi peluh dan nafasnya tercungap-cungap.
"Tempat ni memang keras”, rungut Mamat Bukit sambil merenung lubang yang berasap.
Sebelum saya mengajukan sebarang pertanyaan pada Mamat Bukit, lubang yang berasap itu terus menjadi rata tanpa meninggalkan sebarang kesan.
"Saya mesti mengadakan semah atau jamuan di tempat ini”, Mamat Bukit lalu menandakan tempat itu dengan sebatang kayu yang bercabang dua.
Salah satu cabang itu Mamat Bukit ikatkan dengan kain warna hitam.
Mamat Bukit terus duduk bersila di situ, badannya terus menggeletar, suaranya juga berubah parau dan kasar, kemudian bertukar macam suara orang perempuan.
Mamat Bukit terus menghempas-hempaskan badannya di bumi, macam ayam kena sembelih.
Kelakuan Mamat Bukit itu mengejutkan kawan-kawannya yang sedang tidur. Mereka terus menerkam ke arah Mamat Bukit yang tidak sedarkan diri.
Samad Perang terus mencangkung di depannya.
"Hai Datuk penunggu, kenapa anak cucu yang mencari makan di sini diganggu?”, kata Samad Perang.
Mamat Bukit yang berguling-guling atas tanah berhenti berguling, terus duduk mencangkung sambil menekankan mulutnya ke bumi. Saya lihat bibirnya penuh dengan tanah.
"Datuk mahu makan? Boleh kami beri”, sambung Samad Perang.
"Ya, kambing jantan warna putih, disembelih, tujuh sikat pisang emas”, balas Mamat Bukit dalam suara seorang perempuan, Mamat Bukit terus menggilai.
"Lagi apa tuk penunggu mahu?"
"Adakan jamuan itu pada tiap-tiap tahun, nanti kau orang senang mencari rezeki di sini."
"Baik Datuk penunggu."
"Ingat pesan aku."
Begitulah lebih kurang percakapan Samad Perang dengan penunggu rotan yang meresap ke dalam diri Mamat Bukit.
Bila percakapan itu selesai, Mamat Bukit pun pulih seperti biasa. Datuk tidak campur tangan dalam urusan tersebut.
Pagi itu, setelah Datuk menunaikan sembahyang Subuh serta mandi embun, barulah Datuk bertanya pada Mamat Bukit tentang peristiwa yang dialaminya pada sebelah malam.
Datuk mengakui tentang kehebatan Mamat Bukit, menurut Datuk kalau calang-calang orang tidak mungkin boleh berhadapan dengan kejadian yang aneh itu.
Nampaknya Mamat Bukit kurang senang dengan pujian yang diberikan oleh Datuk.
"Saya buat apa yang saya tahu”, beritahu Mamat Bukit pada Datuk.
"Dari mana kau belajar semuanya ini Mamat?"
"Dari arwah orang tua saya."
"Cuma ada satu saja yang cacatnya dalam perkara ini."
Saya lihat muka Mamat Bukit segera berubah. Dia bagaikan terkejut menerima kata-kata Datuk yang tidak diduga sama sekali terkeluar dari mulut Datuk.
Dengan pandangan yang tajam dia merenung muka Datuk lama-lama.
"Apa maksud dengan cacat yang awak katakan?”, soal Mamat Bukit.
"Saya tahu, ayah awak memang handal di hutan, saya berkawan dengannya. Saya merasa megah kerana awal sedikit sebanyak dapat ilmu darinya.”
"Lagi?"
"Sejak semalam saya belum melihat awak bersembahyang sebagai tanda bersyukur pada pemberianNya, awak menerima rezekiNya, tapi awak tidak pernah mengingatinya.
"Maafkan saya kalau tersinggung, sebagai seorang Islam saya cuma mengingatkan awak. Saya tidak memaksa”, dengan tenang Datuk bersuara. Mamat Bukit tersenyum.
Dan Mamat Bukit tidak mahu memperkatakan perkara yang Datuk sebutkan itu.
Dia mengalih persoalan pada penunggu rotan semambu yang mahukan kambing putih, secara tidak langsung dia membebankan masalah itu pada diri Datuk.
Cara halus dia seolah-olah mahukan Datuk mengadakan kambing putih itu.
Datuk yang mengerti dengan tujuan dan maksud Mamat Bukit itu, menolak permintaan itu dengan secara terhormat.
Dan Mamat Bukit pula tidak merasa hampa atau kecewa dengan sikap Datuk itu, malah kalau Datuk tidak mahu mengadakan, dia sendiri akan berusaha hingga perkara yang dijanjikannya itu pasti terlaksana.
“Usahlah buat kerja membazir tu Mamat. Itu perbuatan syaitan”, kata Datuk dengan tenang. Mamat Bukit gelengkan kepala beberapa kali.
“Ini janji.”
“Janji dengan Syaitan.”
“Tidak, dengan penunggu”, suara Mamat Bukit mula meninggi.
Matanya merah merenung muka Datuk dan kawan-kawannya juga merasa kurang senang dengan tindak-tanduk Datuk itu.
Dollah Beranggas menghampiri Datuk. Dua kali bahu kanan Datuk ditepuknya.
“Awak tak usah masuk campur, ini urusan kami selesaikan sendiri”, kata Dollah Beranggas.
“Tapi perbuatan itu tak kena pada tempatnya, bertentangan dengan hukum agama Islam.”
“Awak tahu, bila hajat penunggu ditunaikan, rotan akan menjadi-jadi dan rezeki kami akan bertambah.”
Datuk menggigit bibir, muka Dollah Beranggas direnungnya. Saya lihat Mamat Bukit, Samad Perang dan Udin Candung tersenyum sinis pada Datuk.
“Kerja mengarut.”
“Mengarut pada awak, pada kami tidak”, sahut Mamat Bukit.
Datuk terus membisu dan beredar dari situ menuju ke belakang bangsal. Tidak siapa yang tahu kenapa Datuk pergi ke belakang bangsal.
Saya tahu, Datuk kurang senang dengan peristiwa yang terjadi, begitu dengan Mamat Bukit dan kawan-kawannya.
Mereka merasakan kehadiran Datuk dalam kumpulan mereka tidak mendatangkan manfaat yang besar.
Samad Perang secara terang-terangan menyalahkan Mamat Bukit yang membenarkan Datuk ikut serta dalam kumpulan mereka.
Mamat Bukit tetap mempertahankan apa yang dibuatnya itu memang kena pada tempatnya.
Mujurlah perbalahan kecil yang terjadi antara mereka tidak sampai didengar oleh Datuk. Kalau Datuk dengar sudah tentu perasaannya tersinggung.
“Jangan beritahu pada Datuk awak, apa yang awak dengar...”, Mamat Bukit mengingatkan saya. Tanpa berfikir panjang saya anggukkan kepala.
Matahari pagi kian meninggi, jalur sinarnya memanah pada daun-daun kering di bumi.
Mamat Bukit dan kawan-kawannya sudah pun memikul gulung rotan ke atas bahu masing-masing. Bersedia untuk pulang.
“Macam mana ni? Kita balik ikut jalan kita datang atau ikut jalan lain?”, Udin Candung bersuara.
“Ikut jalan datang”, balas Samad Perang.
Saya merasa kagum dengan tenaga yang dimiliki oleh mereka. Walaupun tubuh badan mereka agak kecil, tetapi mereka mampu memikul gulung (berkas) rotan yang berat untuk meredah hutan dan paya.
“Nanti dulu, sahabat saya belum bersedia”, suara Mamat Bukit meninggi.
Dan kawan-kawannya terpaksa meletakkan kembali gulung rotan di bahu ke tanah.
Semua biji mata kawan-kawan Mamat Bukit merenung pada Datuk yang muncul dari belakang bangsal. Dia tangan kanannya ada sebatang kayu sebesar ibu jari kaki.
“Buat apa kayu tu?”, tanya Mamat Bukit.
“Buat tongkat, waktu turun dari bukit.”
“Saya dah bertahun masuk hutan, tak pernah bawa kayu bila turun bukit.”
"Itu awak, sudah biasa. Saya tak pandai."
Kawan-kawan Mamat Bukit terus ketawa mendengar jawapan dari Datuk itu.
Datuk terus mengambil rotan semambunya dalam bangsal, tiba-tiba Datuk berpatah balik, mukanya nampak cemas.
"Kenapa?", soal Mamat Bukit.
"Ular tedung dekat rotan semambu saya."
"Itulah, awak tak percaya pada penunggu. Sekarang apa dah jadi?”, cara mendadak saja Samad Perang bersuara yang diakhiri dengan senyum menyindir.
"Jangan timbulkan masalah lagi”, Mamat Bukit menengking Samad Perang dan di wajahnya terpamer rasa kesal atas tindakannya itu.
Mamat Bukit terus mengajak Datuk ke tempat rotan semambu. Saya pun ikut serta.
Apa yang dikatakan oleh Datuk itu memang benar. Seekor ular tedung berlingkar atas batang rotan semambu milik Datuk.
Bila mendengar bunyi tapak kaki kami, ular itu bergerak-gerak dan panggungkan kepala.
Sebenarnya, kalau Datuk tidak memanggil Mamat Bukit pun masalah itu boleh diatasi.
Datuk boleh mengusir ular itu dengan kayu atau membunuhnya.
Ada masalah yang lebih besar dari itu Datuk boleh menyelesaikannya, kenapa masalah sekecil ini Datuk memerlukan tenaga orang lain?
Tindak-tanduk Datuk itu menimbulkan tanda tanya pada diri saya sendiri. Apakah muslihat Datuk yang sebenar?
Apakah dia mahu menguji kemampuan diri Mamat Bukit atau sekadar mahu tahu sejauh mana Mamat Bukit mempercayai perkara tahyul.
Mamat Bukit hulurkan tangan kirinya pada ular itu. Saya lihat badan ular itu bergerak cepat lalu mematuk tangan Mamat Bukit.
Aneh, Mamat Bukit masih tersenyum dan terus menangkap kepala ular. Dengan ibu jari dan telunjuk dia menekan rahang ular hingga mulutnya terbuka.
Siung (gigi) ular jelas kelihatan. Mamat Bukit tekan siung ular itu pada kayu keras hingga siungnya mengeluarkan air jernih yang agak kental.
"Itu bisa ular”, bisik Datuk pada saya.
Ular di tangan Mamat Bukit jadi lemah. Mamat Bukit melemparkan ular itu ke dalam hutan tebal.
Dengan telapak tangannya, Mamat Bukit mengambil bisa ular yang jatuh atas daun kering dan digosokkan pada kedua belah tangannya.
"Dengan cara ini saya akan kebal dari sebarang bisa ular”, beritahu Mamat Bukit pada Datuk.
"Kau memang hebat Mamat."
"Sebenarnya begini, saya belajar perkara ini semasa saya berada di Siam."
"Macam mana awak boleh ke sana?"
"Panjang ceritanya. Saya ditangkap oleh tentera Jepun dan jadi buruh kereta api maut, saya lari dari kem. Berbulan-bulan duduk dalam hutan.
"Masa itulah saya berjumpa dengan seorang sami”, Mamat Bukit berhenti bercerita.
"Apa yang awak buat dengan sami tu?"
"Dialah yang mengajar saya ilmu ini, tetapi, sebelum itu saya terpaksa makan hempedu ular yang bisa."
"Begitu”, keluh Datuk sambil mengerutkan dahi.
Mamat Bukit terus menepuk-nepuk belakang saya berkali-kali. Datuk terus melihat kawasan sekeliling.
"Jadi ular tadi bukan ular penunggu?", saya bertanya padanya.
"Bukan”, sahut Mamat Bukit lalu menyuruh Datuk mengambil rotan semambu.
Datuk terus ambil rotan semambu, kemudian kami pun menuju ke kawasan lapang depan bangsal.
Samad Perang, Udin Candung dan Dollah Beranggas masih duduk mencangkung di situ.
“Mari, kila beredar sekarang”, Mamat Bukit mengeluarkan perintah.
Kawan-kawannya bangun serentak dan meletakkan gulung rotan ke atas bahu masing-masing.
Mamat Bukit jadi kepala jalan. Datuk berada di belakang sekali. Baru dua tiga rantai melangkah, Mamat memerintahkan kami berhenti.
"Tak seronok rasanya, kawan kita berada di belakang sekali. Kenapa tak ke depan dekat saya”, kata-kata itu Mamat Bukit tujukan pada Datuk.
"Tak apa, biarlah saja jadi ekor jalan."
"Bukan apa-apa, kalau bercerai nanti saya takut awak sesat."
"Dengan izin Allah, saya tak sesat."
Mamat Bukit puas hati dengan penjelasan Datuk itu. Dia meneruskan perjalanan.
Orang yang paling resah sekali dengan sikap Datuk itu ialah Samad Perang. Dia seolah-olah tidak mahu Datuk berada di belakangnya. Kalau boleh biarlah Datuk berada di depannya.
Kenapa Samad Perang bersikap demikian? Saya sendiri pun tidak tahu.
Badan saya mula berpeluh, saya kira orang-orang lain dalam perjalanan juga berpeluh.
Kami sudah pun menuruni tiga buah bukit yang curam. Setiap kali turun bukit saya pasti jatuh kerana tidak pandai mengimbangi badan.
Satu hal yang pasti, dalam perjalanan itu kami tidak banyak bercakap, kecuali ada hal yang penting.
"Sial”, pekik Samad Perang sambil membuangkan gulung rotan di bahu.
Samad Perang terus mencabut golok perak dan mencantas semua pokok-pokok kecil di kelilingnya.
Rambutnya yang digunting pendek kelihatan tegak macam bulu landak, biji natanya mula merah.
Kata-kata yang lahir dari mulutnya tidak menentu dan curang jelas, sukar untuk memahami dengan apa yang dituturkannya.
"Buat bulatan keliling dia. Kalau dia mahu lari, tangkap”, Mamat Bukit mengeluarkan arahan.
Arahan itu segera dipatuhi. Samad Perang terus mengamuk, tidak ada seorang pun yang berani menghampirinya.
"Siapa berani sila rapat, aku keluarkan isi perut kamu semua”, suaranya meninggi.
Golok perak terus diacu-acukan pada kami yang mengelilinginya. Samad Perang gulingkan badan atas tanah.
Habis semua pokok-pokok renek di situ dilanggarnya. Aneh, bajunya tidak koyak, badannya juga tidak luka.
"Aku mahu kambing jantan putih”, suara Samad Perang berlainan benar kali ini.
Parau dan garang. Dia cuba merempuh bulatan yang kami buat.
Dalam masa kelam kabut itu, Mamat Bukit terus mencabut sebatang pokok kecil. Badan Samad Perang dipukulnya bertalu-talu.
Pukulan itu tidak mendatangkan sebarang kesan pada Samad Perang.
Malah, Samad Perang bertambah berang. Kekuatan yang diperlihatkannya amat luar biasa sekali.
Mamat Bukit tidak boleh menahan sabar lagi, bila Samad Perang menendang perut Udin Candung hingga termuntah-muntah.
Udin Candung tersungkur di bumi.
Mamat Bukit segera bertindak. Dia melompat tinggi dan melepaskan satu tendangan kencang di bahu kanan Samad Perang.
Samad Perang tergolek di bumi. Mamat Bukit terus mengikat kedua belah tangan dan kaki Samad Perang dengan rotan.
Kemudian dia menyuruh Dollah Berangas dan Udin Candung membuat pengusung. Cukup cepat mereka bekerja. Tidak sampai satu jam, pengusung pun siap.
"Nampaknya kita terpaksa pikul sampai ke rumah”, kata Mamat Bukit.
Bagi memastikan Samad Perang tidak melompat dari pengusung, badannya diikat dengan rotan pada gelegar pengusung.
Mamat Bukit dan Dollah Berangas di depan, Udin Candung dan Datuk di belakang.
Saya terkecuali dari tugas itu, tetapi, saya terpaksa memikul tiga batang rotan semambu milik Datuk.
Tiga batang rotan semambu bukanlah berat sangat, tetapi, rotan semambu yang saya pikul ini beratnya agak aneh, macam berat seguni padi.
Saya teringat pesan Datuk katanya, bila hati merasa cemas atau sangsi terhadap sesuatu bacalah ayat Kursi.
Hal itu segera saya lakukan. Rotan semambu yang terasa berat itu menjadi ringan kembali.
Memikul manusia dalam hutan bukanlah satu perkara yang mudah. Kerana semangat setia kawan yang kental, kerja yang sukar itu menjadi senang.
Lebih kurang pukul dua petang, pengusung yang membawa Samad Perang terdampar di halaman rumahnya.
Kaum keluarganya jadi gempar. Ada yang menangis dan ada yang meratap. Pada sangkaan mereka Samad Perang sudah meninggal dunia.
Bila keadaan sebenar dijelaskan oleh Mamat Bukit, suasana menjadi aman dan tenang.
Samad Perang dibawa ke dalam rumah dan dibaringkan di ruang anjung. Semua ikatannya dibuka. Mamat Bukit meraba pangkal lehernya lalu menekan salah satu urat di situ.
Samad Perang membukakan kedua belah kelopak matanya. Dia senyum seketika dan lepas itu dia terus melompat dan bertempik, semua barang yang ada berada di anjung habis ditendangnya.
Samad Perang menjelirkan lidahnya macam anjing kehausan dan sepasang matanya yang merah merenung tajam ke wajah isterinya yang berdiri tidak jauh darinya.
Gerakannya cukup pantas, dengan sekelip mata sahaja dia menerkam ke arah isterinya dan terus mencekik leher isterinya.
Mamat Bukit segera bertindak. Dia melepaskan satu penumbuk kencang di dagu Samad Perang.
Saya lihat Samad Perang terus jatuh. Udin Candung terus memapah isteri Samad Perang dalam keadaan separuh sedar dan pengsan ke ruang tengah rumah.
Beberapa orang perempuan terus memberi rawatan kilat pada isteri Samad Perang.
Di luar dugaan, Samad Perang yang kena penumbuk kencang itu boleh bangun dengan segera dan terus menyerang Mamat Bukit.
Datuk, Udin Candung serta Dollah Berangas terus menangkap Samad Perang tetapi usaha itu gagal.
Samad Perang terlalu gagah. Dengan sekali pusing sahaja ketiga-tiga orang itu terhumban atas lantai anjung rumah.
Dahi Udin Candung berdarah kena tiang. Bibir Dollah Beranggas pecah kena lantai. Pangkal kening Datuk bengkak kena penumbuk.
Mamat Bukit berhempas mahu melepaskan dirinya dari pelukan Samad Perang.
Setiap kali Samad Perang menggigit tubuhnya, muka Mamat Bukit berkerut menahan kesakitan.
Darah membasahi baju Mamat Bukit. Satu pemandangan yang amat ngeri bagi diri saya.
"Tolong saya, tangkap dia”, jerit Mamat Bukit.
Dengan serentak Datuk dan Dollah Beranggas memeluk tubuh Samad Perang dari belakang.
Kedua-duanya kena penendang, tersungkur atas lantai. Udin Candung pula bertindak dan mengalami nasib yang sama.
"Kita tangkap kakinya”, Dollah Beranggas beri cadangan.
"Ya, mari kita cuba”, jawab Udin Candung.
"Satu cara yang baik”, sahut Datuk.
Serentak mereka bertiga memaut kaki Samad Perang dan Samad Perang pun rebah.
Mamat Bukit berjaya melepaskan dirinya dan terus memeluk tubuh Samad Perang.
Tamat siri 55/284
BACA: SBDJ Siri 54: Penunggu Rotan Semambu
BACA: Siri Bercakap Dengan Jin (Koleksi Lengkap)
-SENTIASAPANAS.COM
Artikel ini hanyalah simpanan cache dari url asal penulis yang berkebarangkalian sudah terlalu lama atau sudah dibuang :
http://www.sentiasapanas.com/2019/04/sbdj-siri-55-mamat-bukit-yang-gagah.html
 PING BABAB : Raksasa Aggregator Malaysia
PING BABAB : Raksasa Aggregator Malaysia