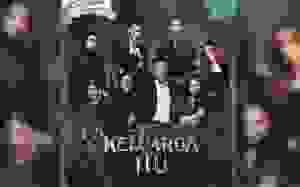Nabi Tidak Memerintahkan Untuk Menginjak Kaki Temannya Saat Shalat Berjamaah
Nashiruddin al-Albani adalah sosok yang kontroversial. Bagi para pengikutnya, al-Albani disebut sebagai muhadits abad ini. Sementara sebagian besar muslimin mengatakan al-Albani bukanlah seorang muhaddits, yang derajatnya sangat jauh untuk menyandang gelar sebagai ahli hadits.
Semasa hidupnya al-Albani lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membaca hadits-hadits secara otodidak di balik perpustakaan, tidak belajar hadits kepada guru ahli hadits (http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Nashiruddin_Al-Albani). Begitu tertariknya al-Albani terhadap hadits, sampai-sampai toko reparasi jamnya pun memiliki dua fungsi, sebagai tempat mencari nafkah dan tempat belajar hadits, dikarenakan bagian belakang tokonya itu sudah diubahnya sedemikian rupa menjadi perpustakaan pribadi. Bahkan waktunya mencari nafkah pun tak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan waktunya untuk belajar, yang pada saat-saat tertentu hingga (total) 18 jam dalam sehari untuk belajar, di luar waktu-waktu shalat dan aktivitas lainnya (Asy Syariah Vol. VII/No. 77/1432/2011 hal. 12, Qomar Suaidi, Lc).
Nashiruddin al-Albani pun secara rutin mengunjungi perpustakaan azh-Zhahiriyyah di Damaskus untuk membaca buku-buku yang tak biasanya didapatinya di toko buku. Dan perpustakaan pun menjadi laboratorium umum baginya, waktu 6-8 jam bisa habis di perpustakaan itu, hanya keluar di waktu-waktu shalat, bahkan untuk makan pun sudah disiapkannya dari rumah berupa makanan-makanan ringan untuk dinikmatinya selama di perpustakaan.
Begitulah sekelumit kehidupan al-Albani yang sangat suka dengan hadits-hadits yang dipelajarinya melalui buku-buku perpustakaan. Tak heran, pemikiran-pemikiran al-Albani seringkali berseberangan dan tidak sesuai dengan pendapat para ulama ahli hadits ahlussunnah wal jama’ah. Dia al-Albani sering melakukan kesalahan dalam menilai suatu hadits, terkadang al-Albani mengatakan suatu hadits itu shahih tapi dalam bukunya yang lain mengatakan tidak shahih, begitupun sebaliknya.
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,“Barangsiapa menguraikan al-Qur’an dengan akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. Ahmad)
Syaikh Nashir al-Asad menjawab pertanyaan ini: “Orang yang hanya mengambil ilmu melalui kitab saja tanpa memperlihatkannya kepada ulama dan tanpa berjumpa dalam majelis-majelis ulama, maka ia telah mengarah pada distorsi. Para ulama tidak menganggapnya sebagai ilmu, mereka menyebutnya shahafi atau otodidak, bukan orang alim. Para ulama menilai orang semacam ini sebagai orang yang dlaif (lemah). Ia disebut shahafi yang diambil dari kalimat tashhif, yang artinya adalah seseorang mempelajari ilmu dari kitab tetapi ia tidak mendengar langsung dari para ulama, maka ia melenceng dari kebenaran. Dengan demikian, sanad dalam riwayat menurut pandangan kami adalah untuk menghindari kesalahan semacam ini” (Mashadir asy-Syi’ri al-Jahili 10)
Orang yang berguru tidak kepada guru tapi kepada buku saja maka ia tidak akan menemui kesalahannya karena buku tidak bisa menegur, tapi kalau guru bisa menegur jika ia salah atau jika ia tak faham ia bisa bertanya, tapi kalau buku jika ia tak faham ia hanya terikat dengan pemahaman dirinya sendiri menurut akal pikirannya sendiri.
Nashiruddin al-Albani dalam kitabnya, Silsilat al-Ahadits as-Shahihah, hal. 6/77 menuliskan :
وقد أنكر بعض الكاتبين في العصر الحاضر هذا الإلزاق, وزعم أنه هيئة زائدة على الوارد, فيها إيغال في تطبيق السنة! وزعم أن المراد بالإلزاق الحث على سد الخلل لا حقيقة الإلزاق, وهذا تعطيل للأحكام العملية, يشبه تماما تعطيل الصفات الإلهية, بل هذا أسوأ منه
Sebagian penulis zaman ini telah mengingkari adanya ilzaq (menempelkan mata kaki, dengkul, bahu) ini, hal ini bisa dikatakan menjauhkan dari menerapkan sunnah. Dia menyangka bahwa yang dimaksud dengan “ilzaq” adalah anjuran untuk merapatkan barisan saja, bukan benar-benar menempel. Hal tersebut merupakan ta’thil (pengingkaran) terhadap hukum-hukum yang bersifat alamiyyah, persis sebagaimana ta’thil (pengingkaran) dalam sifat Ilahiyyah. Bahkan lebih jelek dari itu.
Nashiruddin al-Albani secara tegas memandang bahwa yang dimaksud ilzaq dalam hadits adalah benar-benar menempel. Artinya, sesama mata kaki, sesama dengkul dan sesama bahu harus benar nempel dengan orang di sampingnya. Dan itulah yang dia katakan sebagai sunnah Nabi.
Tak hanya berhenti sampai disitu, al-Albani dalam bukunya juga mengancam mereka yang tidak sependapat dengan pendapatnya, sebagai orang yang ingkar kepada sifat Allah.
Maksudnya kalau orang berpendapat bahwa ilzaq itu hanya sekedar anjuran untuk merapatkan barisan, dan bukan benar-benar saling menempelkan bahu dengan bahu, dengkul dengan dengkul , dan mata kaki dengan mata kaki, sebagai orang yang muatthil. Maksudnya orang itu dianggap telah ingkar terhadap sifat Allah, bahkan keadaanya lebih jelek dari itu.
Untuk itu pendapat al-Albani ini didukung oleh murid-murid setianya. Dimana-mana mereka menegaskan bahwa ilzaq ini disebut sebagai sunnah mahjurah, yaitu sunnah yang telah banyak ditinggalkan oleh orang-orang. Oleh karena itu perlu untuk dihidup-hidupkan lagi di masa sekarang.
Bandingkan pendapat “sesama mereka”. Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berkata:
أن كل واحد منهم يلصق كعبه بكعب جاره لتحقق المحاذاة وتسوية الصف, فهو ليس مقصوداً لذاته لكنه مقصود لغيره كما ذكر بعض أهل العلم, ولهذا إذا تمت الصفوف وقام الناس ينبغي لكل واحد أن يلصق كعبه بكعب صاحبه لتحقق المساواة, وليس معنى ذلك أن يلازم هذا الإلصاق ويبقى ملازماً له في جميع الصلاة.
Setiap masing-masing jamaah hendaknya menempelkan mata kaki dengan jamaah sampingnya, agar shaf benar-benar lurus. Tapi menempelkan mata kaki itu bukan tujuan intinya, tapi ada tujuan lain. Maka dari itu, jika telah sempurna shaf dan para jamaah telah berdiri, hendaklah jamaah itu menempelkan mata kaki dengan jamaah lain agar shafnya lurus. Maksudnya bukan terus menerus menempel sampai selesai shalat. (Lihat : Muhammad bin Shalih al-Utsaimin; w. 1421 H, Fatawa Arkan al-Iman, hal. 1/ 311)
Ternyata Utsaimin sendiri memandang bahwa menempelkan mata kaki itu bukan tujuan inti. Menempelkan kaki itu hanyalah suatu sarana bagaimana agar shaf shalat bisa benar-benar lurus. Jadi, menempelkan mata kaki dilakukan hanya di awal sebelum shalat saja. Dan begitu shalat sudah mulai berjalan, sudah tidak perlu lagi. Maka tidak perlu sepanjang shalat seseorang terus berupaya menempel-nempelkna kakinya ke kaki orang lain, yang membuat jadi tidak khusyu’ shalatnya.
Ulama Bakr Abu Zaid (w. 1429 H) adalah salah seorang ulama Saudi yang pernah menjadi Imam Masjid Nabawi, dan menjadi salah satu anggota Haiah Kibar Ulama Saudi. Dia menulis kitab yang berjudul La Jadida fi Ahkam as-Shalat (Tidak Ada Yang Baru Dalam Hukum Shalat), hal. 13.
Dalam tulisannya Bakr Abu Zaid berpendapat :
وإِلزاق الكتف بالكتف في كل قيام, تكلف ظاهر وإِلزاق الركبة بالركبة مستحيل وإِلزاق الكعب بالكعب فيه من التعذروالتكلف والمعاناة والتحفز والاشتغال به في كل ركعة ما هو بيِّن ظاهر.
Menempelkan bahu dengan bahu di setiap berdiri adalah takalluf (memberat-beratkan) yang nyata. Menempelkan dengkul dengan dengkul adalah sesuatu yang mustahil, menempelkan mata kaki dengan mata kaki adalah hal yang susah dilakukan.
Bakr Abu Zaid melanjutkan:
فهذا فَهْم الصحابي – رضي الله عنه – في التسوية: الاستقامة, وسد الخلل لا الإِلزاق وإِلصاق المناكب والكعاب. فظهر أَن المراد: الحث على سد الخلل واستقامة الصف وتعديله لا حقيقة الإِلزاق والإِلصاق
Inilah yang difahami para shahabat dalam taswiyah shaf: Istiqamah, menutup sela-sela. Bukan menempelkan bahu dan mata kaki. Maka dari itu, maksud sebenarnya adalah anjuran untuk menutup sela-sela, istiqamah dalam shaf, bukan benar-benar menempelkan.
Jadi, menurut Bakr Abu Zaid (w. 1429 H) hadits itu bukan berarti dipahami harus benar-benar menempelkan mata-mata kaki, dengkul dan bahu tapi hanya meluruskan Shaf.
Ibnu Rajab al-Hanbali (w. 795 H) termasuk ulama besar yang menulis kitab penjelasan dari Kitab Shahih Bukhari.
Ibnu Rajab menuliskan:
حديث أنس هذا: يدل على أن تسوية الصفوف: محاذاة المناكب والأقدام
Hadits Anas ini menunjukkan bahwa yang dimaksud meluruskan shaf adalah lurusnya bahu dan telapak kaki. (Lihat: Ibnu Rajab al-Hanbali; w. 795 H, Fathu al-Bari, hal.6/ 282).
Nampaknya Ibnu Rajab lebih memandang bahwa maksud hadits Anas adalah meluruskan barisan, yaitu dengan lurusnya bahu dan telapak kaki.
Komentar Ibnu Hajar (w. 852 H), Beliau Ibnu Hajar al-Asqalani menuliskan:
الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْمُبَالَغَةُ فِي تَعْدِيلِ الصَّفِّ وَسَدِّ خَلَلِهِ
Maksud hadits ”ilzaq” adalah berlebih-lebihan dalam meluruskan shaf dan menutup celah. [Ibnu Hajar, Fathu al-Bari, hal. 2/211]
Memang disini beliau tidak secara spesifik menjelaskan harus menempelkan mata kaki, dengkul dan bahu. Karena maksud haditsnya adalah untuk berlebih-belihan dalam meluruskan shaf dan menutup celahnya.
Point-Point Penting
Diatas sudah dipaparkan beberapa pemahaman ulama terkait haruskah mata kaki selalu ditempel-tempelkan dengan sesama jamaah dalam satu shaf.
Sekarang mari kita lanjutkan penelitian terhadap hadits yang terkait.
Hadits Riwayat Anas bin Malik:
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ»
Dari Anas bin Malik dari Nabi Muhammad shallallah ‘alaih wasallam: ”Tegakkanlah shaf kalian, karena saya melihat kalian dari belakang pundakku.” ada diantara kami orang yang menempelkan bahunya dengan bahu temannya dan telapak kaki dengan telapak kakinya.(HR. Al-Bukhari)
Al-Imam Al-Bukhari mencantumkan teks hadits ini dalam kitab As-Shahih, pada Bab Merapatkan Pundak Dengan Pundak dan Telapak Kaki dengan Telapak Kaki, hal. 1/146.
Catatan:
Riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahuanhu menggunakan redaksi [القدم], sehingga Imam Bukhari pun mengawali hadits dengan judul merapatkan pundak dengan pundak dan telapak kaki dengan telapak kaki.
Hadits Riwayat an-Nu’man bin Basyir:
وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ: رَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ
An-Nu’man bin Basyir berkata: Saya melihat laki-laki diantara kami ada yang menempelkan mata kakinya dengan mata kaki temannya. (HR. Bukhari)
Hadits kedua ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab As-Shshahih, pada bab yang sama dengan hadits di atas.
Catatan:
Hadits kedua ini mu’allaq dalam shahih Bukhari, hadits ini lengkapnya adalah:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ, حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا, عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْجَدَلِيِّ, قَالَ أَبِي: وحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا, عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ أَبِي الْقَاسِمِ, أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ, قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّاسِ, فَقَالَ: ” أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ, ثَلَاثًا وَاللهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ” قَالَ: ” فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ, وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِهِ وَمَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِهِ
An-Nu’man bin Basyir berkata: Rasulullah menghadap kepada manusia, lalu berkata: Tegakkanlah shaf kalian!; tiga kali. Demi Allah, tegakkanlah shaf kalian, atau Allah akan membuat perselisihan diantara hati kalian. Lalu an-Nu’man bin Basyir berkata: Saya melihat laki-laki menempelkan mata kakinya dengan mata kaki temannya, dengkul dengan dengkul dan bahu dengan bahu.
Selain diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadits-hadits ini juga diriwayatkan oleh para ulama hadits, diantaranya:
Al-Imam Abu Daud dalam kitab Sunan-nya, 1/ 178,
Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad-nya, hal. 30/378,
Al-Imam Ad-Daraquthni dalam kitab Sunan-nya hal. 2/28,
Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunan-nya hal. 1/123]
Catatan Penting:
Setelah Nabi memerintahkan menegakkan shaf, shahabat yang bernama An-Nu’man bin Basyir radhiyallahuanhu melihat seorang laki-laki yang menempelkan mata kaki, dengkul dan bahunya kepada temannya.
Pertanyaannya adalah:
Apakah menempelkan mata kaki itu sunnah Nabi shallallahu alaihi wasallam atau bukan?
Dalam arti apakah hal itu merupakan contoh langsung dari Nabi shallallahu alaihi wasallam atau bentuk perintah yang secara nash beliau shallallahu alaihi wasallam menyebut: “harus menempel” ?
Menempelkan mata kaki dalam shaf bukan tindakan atau anjuran Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam
Bukankah haditsnya jelas Shahih dalam Shahih Bukhari dan Abu Daud?
Iya sekilas memang terkesan bahwa menempelkan itu perintah beliau shallallahu ‘alaihi wasallam Tapi keshahihan hadits saja belum cukup tanpa pemahaman yang benar terhadap hadits shahih.
Jika kita baca seksama teks hadits dua riwayat diatas, kita dapati bahwa ternyata yang Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam anjurkan adalah menegakkan shaf. Perhatikan redaksinya :
أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ
Tegakkah barisan kalian
Itu yang beliau shallallahu ‘alaihi wasallam katakan. Sama sekali beliau shallallahu ‘alaihi wasallam tidak berkata, ”Tempelkanlah mata kaki kalian!”. Dan beliau juga tidak main ancam siapa yang tidak melakukannya dianggap telah kafir atau ingkar dengan sifat-sifat Allah. Yang bilang seperti itu hanya Nashiruddin Al-Albani seorang. Para ulama sepanjang zaman tidak pernah berkata seperti itu, kecuali murid-murid pendukungnya saja.
Menempelkan mata kaki adalah pemahaman salah satu dari Sahabat
Coba kita baca lagi haditsnya dengan seksama. Dalam riwayatnya disebutkan:
[وَكَانَ أَحَدُنَا] dan salah satu dari kami
[رَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا] saya melihat seorang laki-laki dari kami
[فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ] saya melihat seorang laki-laki
Meskipun dengan redaksi yang berbeda, tetapi kesemuanya merujuk pada makna bahwa ”salah satu” sahabat Nabi ada yang melakukan hal itu. Maka hal itu adalah perbuatan dari salah satu sahabat Nabi, hasil dari pemahamannya setelah mendengar perintah Nabi agar menegakkan shaf.
Terkait ucapan atau perbuatan shahabat, Al-Amidi (w. 631 H) salah seorang pakar Ushul Fiqih menyebutkan:
ويدل على مذهب الأكثرين أن الظاهر من الصحابي أنه إنما أورد ذلك في معرض الاحتجاج وإنما يكون ذلك حجة إن لو كان ما نقله مستندا إلى فعل الجميع لأن فعل البعض لا يكون حجة على البعض الآخر ولا على غيرهم
Menurut madzhab kebanyakan ulama’, perbuatan shahabi menjadi hujjah jika didasarkan pada perbuatan semua shahabat. Karena perbuatan sebagian tidak menjadi hujjah bagi sebagian yang lain, ataupun bagi orang lain. (Lihat :Al-Amidi; w. 631 H, Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, hal. 2/99)
Jadi, menempelkan mata kaki itu bisa menjadi hujjah jika dilakukan semua shahabat. Dari redaksi hadits, kita dapati bahwa menempelkan mata kaki dilakukan oleh seorang laki-laki pada zaman Nabi. Kita tidak tahu siapakah lelaki itu. Lantas bagaimana dengan Anas yang telah meriwayatkan hadits?
Anas tidak melakukan hal itu
Jika kita baca teks hadits dari Anas bin Malik dan An-Nu’man bin Basyir di atas, sebagai dua periwayat hadits, ternyata mereka berdua hanya melihat saja. Mereka malah tidak melakukan apa yang mereka lihat.
Kenapa?
Karena yang melakukannya bukan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sendiri. Dan para shahabat yang lain juga tidak melakukannya. Yang melakukannya hanya satu orang saja. Itupun namanya tidak pernah disebutkan alias anonim.
Hal itu diperkuat dengan keterangan Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H) melanjutkan riwayat Anas bin Malik:
وَزَادَ مَعْمَرٌ فِي رِوَايَتِهِ وَلَوْ فَعَلْتُ ذَلِكَ بِأَحَدِهِمُ الْيَوْمَ لَنَفَرَ كَأَنَّهُ بغل شموس
Ma’mar menambahkan dalam riwayatnya dari Anas; jika saja hal itu saya lakukan sekarang dengan salah satu dari mereka saat ini, maka mereka akan lari sebagaimana keledai yang lepas. [Ibnu Hajar, Fathu al-Bari, hal. 2/211]
Jika menempelkan mata kaki itu sungguh-sungguh anjuran Nabi, maka mereka sebagai salaf yang shalih tidak akan lari dari hal itu dan meninggalkannya.
Perkataan Anas bin Malik, ”jika saja hal itu saya lakukan sekarang” memberikan pengertian bahwa Anas sendiri tidak melakukannya saat ini.
Ilmu agama adalah ilmu yang diwariskan dari ulama-ulama terdahulu yang tersambung kepada lisannya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda yang artinya “Sampaikan dariku sekalipun satu ayat dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari Bani Isra’il dan itu tidak apa (dosa). Dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka” (HR Bukhari).
Hadits tersebut bukanlah menyuruh kita menyampaikan apa yang kita baca dan pahami sendiri dari kitab atau buku.
Hakikat makna hadits tersebut adalah kita hanya boleh menyampaikan satu ayat yang diperoleh dan didengar dari para ulama yang sholeh dan disampaikan secara turun temurun yang bersumber dari lisannya Sayyidina Muhammad Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Oleh karenanya ulama dikatakan sebagai pewaris Nabi.
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Ulama adalah pewaris para nabi” (HR At-Tirmidzi).
Ulama pewaris Nabi artinya menerima dari ulama-ulama yang sholeh sebelumnya yang tersambung kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.
Pada hakikatnya Al Qur’an dan Hadits disampaikan tidak dalam bentuk tulisan namun disampaikan melalui lisan ke lisan para ulama yang sholeh dengan imla atau secara hafalan.
Dalam khazanah Islam, metode hafalan merupakan bagian integral dalam proses menuntut ilmu. Ia sudah dikenal dan dipraktekkan sejak zaman baginda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Setiap menerima wahyu, beliau langsung menyampaikan dan memerintahkan para sahabat untuk menghafalkannya. Sebelum memerintahkan untuk dihafal, terlebih dahulu beliau menafsirkan dan menjelaskan kandungan dari setiap ayat yang baru diwahyukan.
Jika kita telusuri lebih jauh, perintah baginda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam untuk menghafalkan Al-Qur’an bukan hanya karena kemuliaan, keagungan dan kedalaman kandungannya, tapi juga untuk menjaga otentisitas Al-Qur’an itu sendiri. Makanya hingga kini, walaupun sudah berusia sekitar 1400 tahun lebih, Al-Qur’an tetap terjaga orisinalitasnya. Kaitan antara hafalan dan otentisitas Al-Qur’an ini tampak dari kenyataan bahwa pada prinsipnya, Al-Qur’an bukanlah “tulisan” (rasm), tetapi “bacaan” (qira’ah). Artinya, ia adalah ucapan dan sebutan.
Proses turun-(pewahyuan)-nya maupun penyampaian, pengajaran dan periwayatan-(transmisi)-nya, semuanya dilakukan secara lisan dan hafalan, bukan tulisan. Karena itu, dari dahulu yang dimaksud dengan “membaca” Al-Qur’an adalah membaca dari ingatan (qara’a ‘an zhahri qalbin).
Dengan demikian, sumber semua tulisan itu sendiri adalah hafalan, atau apa yang sebelumnya telah tertera dalam ingatan sang qari’. Sedangkan fungsi tulisan atau bentuk kitab sebagai penunjang semata.
Allah ta’ala berfirman yang artinya, “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar“. (QS at-Taubah [9]:100)
Dari firmanNya tersebut dapat kita ketahui bahwa orang-orang yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang mengikuti Salafush Sholeh. Sedangkan orang-orang yang mengikuti Salafush Sholeh yang paling awal dan utama adalah Imam Mazhab yang empat.
Memang ada mazhab yang lain selain dari Imam Mazhab yang empat namun pada kenyataannya ulama yang memiliki ilmu riwayah dan dirayah dari Imam Mazhab yang lain sudah sukar ditemukan pada masa kini.
Tentulah kita mengikuti atau taqlid kepada Imam Mazhab yang empat dengan merujuk kepada Al Qur’an dan As Sunnah. Imam Mazhab yang empat patut untuk diikuti oleh kaum muslim karena jumhur ulama telah sepakat dari dahulu sampai sekarang sebagai para ulama yang berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak, pemimpin atau imam ijtihad dan istinbat kaum muslim.
Kelebihan lainnya, Imam Mazhab yang empat adalah masih bertemu dengan Salafush Sholeh.
Contohnya Imam Syafi”i ~rahimahullah adalah imam mazhab yang cukup luas wawasannya karena bertemu atau bertalaqqi (mengaji) langsung kepada Salafush Sholeh dari berbagai tempat, mulai dari tempat tinggal awalnya di Makkah, kemudian pindah ke Madinah, pindah ke Yaman, pindah ke Iraq, pindah ke Persia, kembali lagi ke Makkah, dari sini pindah lagi ke Madinah dan akhirnya ke Mesir. Perlu dimaklumi bahwa perpindahan beliau itu bukanlah untuk berniaga, bukan untuk turis, tetapi untuk mencari ilmu, mencari hadits-hadits, untuk pengetahuan agama. Jadi tidak heran kalau Imam Syafi’i ~rahimahullah lebih banyak mendapatkan hadits dari lisannya Salafush Sholeh, melebihi dari yang didapat oleh Imam Hanafi ~rahimahullah dan Imam Maliki ~rahimahullah.
Imam Mazhab yang empat adalah para ulama yang sholeh dari kalangan “orang-orang yang membawa hadits” yakni membawanya dari Salafush Sholeh yang meriwayatkan dan mengikuti sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.
Jadi kalau kita ingin ittiba li Rasulullah (mengikuti Rasulullah) atau mengikuti Salafush Sholeh maka kita menemui dan bertalaqqi (mengaji) dengan para ulama yang sholeh dari kalangan “orang-orang yang membawa hadits”. Para ulama yang sholeh dari kalangan “orang-orang yang membawa hadits” adalah para ulama yang sholeh yang mengikuti salah satu dari Imam Mazhab yang empat. Para ulama yang sholeh yang mengikuti dari Imam Mazhab yang empat adalah para ulama yang sholeh yang memiliki ketersambungan sanad ilmu (sanad guru) dengan Imam Mazhab yang empat atau para ulama yang sholeh yang memiliki ilmu riwayah dan dirayah dari Imam Mazhab yang empat.
Jadi bermazhab dengan Imam Mazhab yang empat adalah sebuah kebutuhan bagi kaum muslim yang tidak lagi bertemu dengan Rasulullah maupun Salafush Sholeh.
Cara menelusuri kebenaran adalah melalui para ulama yang sholeh yang memiliki sanad ilmu (sanad guru) tersambung kepada lisannya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam karena kebenaran dari Allah ta’ala dan disampaikan oleh RasulNya
Pada asalnya, istilah sanad atau isnad hanya digunakan dalam bidang ilmu hadits (Mustolah Hadits) yang merujuk kepada hubungan antara perawi dengan perawi sebelumnya pada setiap tingkatan yang berakhir kepada Rasulullah –Shollallahu ‘alaihi wasallam– pada matan haditsnya.
Namun, jika kita merujuk kepada lafadz Sanad itu sendiri dari segi bahasa, maka penggunaannya sangat luas. Dalam Lisan Al-Arab misalnya disebutkan: “Isnad dari sudut bahasa terambil dari fi’il “asnada” (yaitu menyandarkan) seperti dalam perkataan mereka: Saya sandarkan perkataan ini kepada si fulan. Artinya, menyandarkan sandaran, yang mana ia diangkatkan kepada yang berkata. Maka menyandarkan perkataan berarti mengangkatkan perkataan (mengembalikan perkataan kepada orang yang berkata dengan perkataan tersebut)“.
Ibnul Mubarak berkata:”Sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang diinginkannya (dengan akal pikirannya sendiri).” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Muqoddimah kitab Shahihnya 1/47 no:32 ).
Tanda atau ciri seorang ulama tidak terputus sanad guru (sanad ilmu) adalah pemahaman atau pendapat ulama tersebut tidak menyelisihi pendapat gurunya dan guru-gurunya terdahulu hingga tersambung kepada Rasulullah serta berakhlak baik.
Asy-Syeikh as-Sayyid Yusuf Bakhour al-Hasani menyampaikan bahwa, “Maksud dari pengijazahan sanad itu adalah agar kamu menghafazh bukan sekadar untuk meriwayatkan tetapi juga untuk meneladani orang yang kamu mengambil sanad daripadanya, dan orang yang kamu ambil sanadnya itu juga meneladani orang yang di atas di mana dia mengambil sanad daripadanya dan begitulah seterusnya hingga berujung kepada kamu meneladani Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Dengan demikian, keterjagaan al-Qur’an itu benar-benar sempurna baik secara lafazh, makna dan pengamalan“.
Imam Syafi’i ~rahimahullah mengatakan “Tiada ilmu tanpa sanad”.
Imam Malik ~rahimahullah berkata: “Janganlah engkau membawa ilmu (yang kau pelajari) dari orang yang tidak engkau ketahui catatan (riwayat) pendidikannya (sanad ilmu) dan dari orang yang mendustakan perkataan manusia (ulama) meskipun dia tidak mendustakan perkataan (hadits) Rasulullah shallallahu alaihi wasallam”.
Al-Hafidh Imam Attsauri ~rahimahullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga”.
Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy, quddisa sirruh (Makna tafsir QS.Al-Kahfi 60); “Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya gurunya syetan” (Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203).
Jadi fitnah tanduk syaitan adalah fitnah dari orang-orang yang menjadikan gurunya syaitan karena memahami Al Qur’an dan Hadits bersandarkan mutholaah (menelaah kitab) secara otodidak (shahafi) dengan akal pikirannya sendiri.
Nashiruddin al-Albani menyampaikan bahwa,
“Sebenarnya manusia itu terbagi menjadi tiga, yaitu muqallid (orang yang taqlid), muttabi’ (orang yang mengikuti) dan mujtahid. Orang yang mampu membandingkan madzhab-madzhab yang ada dan memilih yang lebih dekat pada al-Qur’an adalah muttabi’. Jadi muttabi’ itu derajat tengah, antara taqlid dan ijtihad.”
Pernyataan al-Albani itu diucapkan dalam dialog antara seorang tokoh penganjur anti-madzhab dengan ulama ahlussunnah asy-Syaikh Muhammad Said Ramadhan al-Buthi. Meskipun dalam tulisannya, Syaikh al-Buthi tidak menuliskan nama tokoh tersebut, akan tetapi pembaca akan mudah menebak tokoh yang dimaksudkan, yakni Nashiruddin al-Albani, ulama Salafi.
Berikut kutipan dialog selengkapnya:
….
al-Albani: “Manusia terbagi menjadi tiga orang: muqallid, muttabi’, dan mujtahid. Orang yang bisa membandingkan madzhab-madzhab dan menyeleksi mana yang lebih dekat dengan al-Qur’an adalah muttabi’, yakni level menengah antara taklid dan ijtihad.”
Syaikh al-Buthi: “Lalu apa kewajiban muqallid?“
al-Albani: “Bertaklid kepada para mujtahid yang disepakati.”
Syaikh al-Buthi: “Apakah seorang muqallid berdosa jika ia bertaklid pada salah satu mujtahid, konsisten padanya, dan tidak berpindah ke yang lain?“
al-Albani: “Ya, hal itu haram baginya.”
Syaikh al-Buthi: “Apa dalil dari keharaman itu?“
al-Albani: “Dalilnya, dia telah mengikuti secara konsisten terhadap sesuatu, padahal hal itu tidak diwajibkan Allah ‘azza wa jalla.“
Syaikh al-Buthi: “Anda membaca al-Qur’an dengan bacaan apa dari bacaan yang tujuh (al-Qira’at as-Sab’ah)?“
al-Albani: “Qira’ah Hafsh.”
Syaikh al-Buthi: “Apakah anda konsisten memakai qira’ah tersebut ataukah anda setiap hari memakai bacaan qira’ah yang berbeda?“
al-Albani: “Tidak, saya konsisten memakai Qira’ah Hafsh.”
Syaikh al-Buthi: “Lalu mengapa anda konsisten dengan qira’ah itu, padahal Allah tidak mewajibkan anda untuk membaca al-Qur’an kecuali sebagaimana yang diriwayatkan secara mutawatir dari Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam?“
al-Albani: “Karena saya belum selesai mempelajari qira’ah-qira’ah yang lain. Tidak mudah bagi saya untuk membaca kecuali dengan bacaan ala Hafsh.”
Syaikh al-Buthi: “Ada orang yang mempelajari fiqih madzhab Syafi’i dan belum selesai mempelajari madzhab-madzhab lainnya. Tidak mudah baginya menggunakan fiqih dalam hukum-hukum agama kecuali dengan fiqih Imam Syafi’i. Jika anda wajibkan ia untuk mengetahui ijtihad-ijtihad semua imam hingga ia kuasai semuanya, anda juga wajib mempelajari seluruh qira’ah, sampai semuanya anda gunakan untuk membaca. Jika anda berapologi karena tidak mampu, maka anda harus mentolerir si muqallid itu juga. Pendek kata kami katakan, darimana dalil anda bahwa seorang muqallid harus berganti-ganti madzhab padahal Allah tidak mewajibkan hal itu. Maksudnya, sebagaimana Allah tidak mewajibkan untuk terus menerus mengikuti suatu madzhab, Allah juga tidak mewajibkan muqallid untuk terus menerus berganti-ganti madzhab.”
al-Albani: “Yang haram baginya adalah ia konsisten bermadzhab sementara ia meyakini bahwa Allah tidak memerintahkan hal itu.”
Syaikh al-Buthi: “Itu adalah hal lain (tidak berkaitan dengan bahasan ini -penerj.), itu adalah hal yang sudah benar, tidak diragukan, dan disepakati. Akan tetapi, apakah ia berdosa jika menetapi terus menerus seorang mujtahid padahal ia tahu bahwa Allah tidak mengharuskannya?”
Al-Albani: “Tidak berdosa.”
Syaikh al-Buthi: “Tetapi al-Kurras yang anda ajarkan menyebutkan hal yang berbeda dari apa yang anda katakan. Al-Kurras menergaskan keharaman hal itu, bahkan dalam beberapa keterangan, al-Kurras mengkafirkan orang yang konsisten mengikuti seorang imam tertentu dan tidak berpindah ke imam yang lain.”
al-Albani: “Dimana?”
Kemudian al-Bani merujuk ke al-Kurras, menelaah teksnya dan ungkapannya. Ia lalu merenungkan perkataan penulis kurras: “Bahkan, orang yang konsisten mengikuti suatu madzhab tertentu bagi semua permasalahannya adalah orang yang fanatik, salah, dan bertaklid buta. Mereka adalah orang yang memecah belah agamanya sementara mereka tercerai-berai.”
al-Bani kemudian mengatakan: “Maksud penulis kurras dengan ‘konsisten’ adalah ‘bila meyakini bahwa hal itu wajib secara syara’. Ungakapan itu masih kurang!“
Syaikh al-Buthi: “Apa buktinya kalau ia bermaksud demikian, mengapa tidak anda katakan bahwa penulisnya telah berbuat salah?“
Al-Albani bersikukuh menyatakan bahwa ungkapan al-Kurras benar. Ungkapan tersebut mengandung penakwilan yang dibuang. Penulisnya terjada dari kesalahan
Syaikh al-Buthi: “Tetapi, kalau ditakwil demikian, ungkapan itu tidak berpengaruh apa-apa dan tidak ada gunanya. Tidak ada seorang pun dari umat Islam kecuali mengetahui bahwa mengikuti salah satu imam madzhab empat bukanlah syari’at yang wajib. Tidak seorang pun muslim yang konsisten terhadap madzhab kecuali ia melakukan hal itu karena keinginan dan pilihannya.”
al-Albani: “Bagaimana? Saya mendengar dari banyak orang dan sebagian ulama bahwa konsisten terhadap madzhab tertentu adalah wajib, sampai-sampai tidak boleh berpindah ke madzhab lainnya.”
Syaikh al-Buthi: “Sebutkan satu nama saja pada saya, siapa orang awam atau ulama yang mengatakan pernyataan itu.”
al-Albani terdiam. Ia tidak mau mengakui bahwa perkataan saya (=Syaikh al-Buthi) benar. Ia terus saja mengulang-ulang: “Yang digambarkan oleh penulis kurras adalah bahwa banyak orang yang mengharamkan berpindah-pindah madzhab.”
Syaikh al-Buthi: “Anda tidak akan menemukan satu orang pun hari ini yang meyakini praduga aneh itu. Ya, ada orang-orang yang meriwayatkan dari sebagian ulama generasi akhir masa Utsmaniyah bahwa mereka menganjurkan berpindahnya seseorang yang bermadzhab Hanafi ke madzhab lainnya. Tentu, hal itu -jika memang riwayatnya benar- adalah bentuk lemahnya akal dan fanatisme buta.”
….
Jadi bagi al-Albani, kaum muslim dilarang menjadi muqallid (orang yang taqlid) dan bagi yang tidak berkompetensi sebagai mujtahid seharusnyalah menjadi muttabi’ (orang yang mengikuti) yakni membandingkan madzhab-madzhab yang ada dan memilih yang lebih dekat pada al-Qur’an dan As Sunnah.
Kalau begitu bagaimana nasib kaum muslim yang tidak mempunyai kemampuan untuk membeli kitab-kitab hadits ataupun tidak mempunyai waktu dan kompetensi untuk membandingkan madzhab-madzhab yang ada dan memilih yang lebih dekat pada al-Qur’an dan As Sunnah ? Apakah mereka akan masuk neraka karena mengerjakan perkara terlarang yakni menjadi muqallid (orang yang taqlid)?
Bagaimana dengan seorang muslim yang bodoh yang menggunakan pemahaman subyektifnya dalam memahami telaahnya terhadap al-Qur’an. Ia shalat tidak menghadap kiblat, berbeda dengan semua umat Islam, lalu shalatnya dianggap sah. Seorang lelaki buta menggunakan pemahaman subyektifnya, lalu ia obati seseorang dan orang yang sakit itu meninggal di tangannya. Kepada orang sakit yang meninggal itu ia berkata: “Semoga Allah memberimu kesehatan.”
Jika demikian, kita jadi tidak mengerti, mengapa orang-orang anti-madzhab tidak membiarkan kami untuk menggunakan pemahaman subyektif kami juga, yakni bahwa orang yang tidak tahu hukum-hukum agama dan dalil-dalilnya, harus berpegangan pada salah satu madzhab imam mujtahid. Ia mengikutinya karena memang imam mujtahid adalah orang yang mengerti benar dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul.
KH. Muhammad Nuh Addawami menyampaikan,
“Mengharamkan taqlid dan mewajibkan ijtihad atau ittiba’ dalam arti mengikuti pendapat orang disertai mengetahui dalil-dalilnya terhadap orang awam (yang bukan ahli istidlal) adalah fatwa sesat dan menyesatkan yang akan merusak sendi-sendi kehidupan di dunia ini.
Memajukan dalil fatwa terhadap orang awam sama saja dengan tidak memajukannya. (Lihat Hasyiyah ad-Dimyathi ‘ala Syarh al- Waraqat hal. 23 pada baris ke-12).
Apabila si awam menerima fatwa orang yang mengemukakan dalilnya maka dia sama saja dengan si awam yang menerima fatwa orang yang tidak disertai dalil yang dikemukakan. Dalam artian mereka sama-sama muqallid, sama-sama taqlid dan memerima pendapat orang tanpa mengetahui dalilnya.
Yang disebut muttabi’ “bukan muqallid” dalam istilah ushuliyyin adalah seorang ahli istidlal (mujtahid) yang menerima pendapat orang lain karena dia selaku ahli istidlal dengan segala kemampuannya mengetahui dalil pendapat orang itu.
Adapun orang yang menerima pendapat orang lain tentang suatu fatwa dengan mendengar atau membaca dalil pendapat tersebut padahal sang penerima itu bukan atau belum termasuk ahli istidlal maka dia tidak termasuk muttabi’ yang telah terbebas dari ikatan taqlid.
Pendek kata arti ittiba’ yang sebenarnya dalam istilah ushuliyyin adalah ijtihad seorang mujtahid mengikuti ijtihad mujtahid yang lain.”
Jadi muttabi‘ bukanlah sebagaimana yang dikatakan oleh al-Albani sebagai “derajat tengah, antara taqlid dan ijtihad” namun muttabi‘ adalah orang yang mengikuti pendapat orang lain karena dia ahli istidlal.
Sedangkan orang yang menerima atau mengikuti pendapat orang lain walaupun mengetahui dalilnya namun bukan ahli istidal adalah sama-sama muqallid, sama-sama taqlid dan menerima atau mengikuti pendapat orang tanpa mengetahui dalilnya.
Kompetensi sebagai ahli istidlal adalah sebagaimana yang disampaikan KH. Muhammad Nuh Addawami yakni:
Mengetahui dan menguasai bahasa Arab sedalam-dalamnya, karena al-Quran dan as-Sunnah diturunkan Allah dan disampaikan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dalam bahasa Arab yang fushahah dan balaghah yang bermutu tinggi, pengertiannya luas dan dalam, mengandung hukum yang harus diterima. Yang perlu diketahui dan dikuasainya bukan hanya arti bahasa tetapi juga ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan bahasa arab itu seumpama nahwu, sharaf, balaghah (ma’ani, bayan dan badi’).
Mengetahui dan menguasai ilmu ushul fiqh, sebab kalau tidak, bagaimana mungkin menggali hukum secara baik dan benar dari al-Quran dan as-Sunnah padahal tidak menguasai sifat lafad-lafad dalam al-Quran dan as-Sunnah itu yang beraneka ragam yang masing-masing mempengaruhi hukum-hukum yang terkandung di dalamnya seperti ada lafadz nash, ada lafadz dlahir, ada lafadz mijmal, ada lafadz bayan, ada lafadz muawwal, ada yang umum, ada yang khusus, ada yang mutlaq, ada yang muqoyyad, ada majaz, ada lafadz kinayah selain lafadz hakikat. ada pula nasikh dan mansukh dan lain sebagainya.
Mengetahui dan menguasai dalil ‘aqli penyelaras dalil naqli terutama dalam masalah-masalah yaqiniyah qath’iyah.
Mengetahui yang nasikh dan yang mansukh dan mengetahui asbab an-nuzul dan asbab al-wurud, mengetahui yang mutawatir dan yang ahad, baik dalam al-Quran maupun dalam as-Sunnah. Mengetahui yang shahih dan yang lainnya dan mengetahui para rawi as-Sunnah.
Mengetahui ilmu-ilmu yang lainnya yang berhubungan dengan tata cara menggali hukum dari al-Quran dan as-Sunnah.
Bagi yang tidak memiliki kemampuan, syarat dan sarana untuk menggali hukum-hukum dari al-Quran dan as-Sunnah dalam masalah-masalah ijtihadiyah padahal dia ingin menerima risalah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam secara utuh dan kaffah, maka tidak ada jalan lain kecuali taqlid kepada mujtahid yang dapat dipertanggungjawabkan kemampuannya.
Diantara para mujtahid yang madzhabnya mudawwan adalah empat imam mujtahid, yaitu:
Imam Abu Hanifah Nu’man bin Tsabit;
Imam Malik bin Anas;
Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i ; dan
Imam Ahmad bin Hanbal.
Oleh karenanya setelah masa kehidupan Imam Madzhab yang empat, para mufti yakni orang yang faqih untuk membuat fatwa selalu merujuk kepada salah satu dari Imam Madzhab yang empat.
Perkataan al-Albani yang terkenal adalah “Aku membandingkan antara pendapat semua imam mujtahid serta dalil-dalil mereka lalu aku ambil yang paling dekat terhadap al-Qur’an dan as-Sunnah.”
Secara logika, seseorang yang mampu menghakimi pendapat-pendapat Imam Mazhab yang empat dengan barometer al-Qur’an dan as-Sunnah, jelas ia lebih berkompetensi atau lebih pandai dari Imam Mazhab yang empat.
Imam Ahmad bin Hanbal yang memiliki kompetensi dalam berijtihad dan beristinbat atau berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak, tentu beliau lebih berhak “menghakimi” Imam Mazhab sebelum beliau. Namun kenyataannya, beliau tetap secara independen berijtihad dan beristinbat atas sumber atau bahan yang dimilikinya dengan ilmu yang dikuasainya.
Perbedaan di antara Imam Mazhab yang empat semata-mata dikarenakan terbentuk setelah adanya furu’ (cabang), sementara furu’ tersebut ada disebabkan adanya sifat zanni dalam nash. Oleh sebab itu, pada sisi zanni inilah kebenaran bisa menjadi banyak (relatif), mutaghayirat disebabkan pengaruh bias dalil yang ada. Boleh jadi nash yang digunakan sama, namun cara pengambilan kesimpulannya berbeda.
Jadi perbedaan pendapat di antara Imam Mazhab yang empat tidak dapat dikatakan pendapat yang satu lebih kuat (arjah atau tarjih) dari pendapat yang lainnya atau bahkan yang lebih ekstrim mereka yang mengatakan pendapat yang satu yang benar dan yang lain salah.
Perbedaan pendapat di antara Imam Mazhab yang empat yang dimaksud dengan “perbedaan adalah rahmat”. Sedangkan perbedaan pendapat di antara bukan ahli istidlal adalah kesalahpahaman semata yang dapat menyesatkan orang banyak.
Sementara ada segelintir umat Islam menggabungkan pendapat Imam Mazhab yang empat atau talfiq.
Dalam bahasa Arab, kata talfiq (التَّلْفِيقُ ) berasal dari kata (لَفَّقَ – يُلَفِّقُ – تَلْفِيقاً ) yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain artinya mereka mengikuti seluruh pendapat Imam Mazhab yang empat.
Kita tidak dapat talfiq dalam arti menghakimi pendapat Imam Mazhab yang empat karena selain kita tidak berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak dan kita pun tidak memiliki sumber-sumber untuk melakukan ijtihad dan istinbat sebagaimana yang dimiliki oleh Imam Mazhab yang empat.
Talfiq dalam arti digunakan dikarenakan situasi dan kondisi tidaklah mengapa. Seperti ikutilah apapun mazhab imam sholat karena diriwayatkan oleh Umamah al Bahiliy dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,”Ikatan-ikatan Islam akan lepas satu demi satu. Apabila lepas satu ikatan, akan diikuti oleh lepasnya ikatan berikutnya. Ikatan islam yang pertama kali lepas adalah pemerintahan (kekhalifahan) dan yang terakhir adalah shalat.” (HR. Ahmad)
Orang-orang yang meninggalkan Imam Mazhab yang empat memang sering mengungkapan pendapat seperti “kita harus mengikuti hadits shahih. Bukan mengikuti ulama. Al-Imam Al-Syafi’i sendiri berkata, “Idza shahha al-hadits fahuwa mazhabi (apabila suatu hadits itu shahih, maka hadits itulah mazhabku)”.
Banyak kalangan yang tidak memahami dengan benar perkataan Beliau. Sehingga, jika yang bersangkutan menemukan sebuah hadits shahih yang menurut pemahaman mereka bertentangan dengan pendapat mazhab Syafi’i maka yang bersangkutan langsung menyatakan bahwa pendapat mazhab itu tidak benar, karena Imam Syafi’i sendiri mengatakan bahwa hadits shahih adalah mazhab beliau. Atau ketika seseorang menemukan sebuah hadits yang shahih, yang bersangkutan langsung mengklaim, bahwa ini adalah mazhab Syafi’i.
Imam al-Nawawi sepakat dengan gurunya ini dan berkata, “(Ucapan Al-Syafi’i) ini hanya untuk orang yang telah mencapai derajat mujtahid madzhab. Syaratnya: ia harus yakin bahwa Al-Syafi’i belum mengetahui hadits itu atau tidak mengetahui (status) kesahihannya. Dan hal ini hanya bisa dilakukan setelah mengkaji semua buku Al-Syafi’i dan buku murid-muridnya. Ini syarat yang sangat berat, dan sedikit sekali orang yang mampu memenuhinya. Mereka mensyaratkan hal ini karena Al-Syafi’i sering kali meninggalkan sebuah hadits yang ia jumpai akibat cacat yang ada di dalamnya, atau mansukh, atau ditakhshish, atau ditakwil, atau sebab-sebab lainnya.”
Al-Nawawi juga mengingatkan ucapan Ibn Khuzaimah, “Aku tidak menemukan sebuah hadits yang shahih namun tidak disebutkan Al-Syafii dalam kitab-kitabnya.” Ia berkata, “Kebesaran Ibn Khuzaimah dan keimamannya dalam hadits dan fiqh, serta penguasaanya akan ucapan-ucapan Al-Syafii, sangat terkenal.” [“Majmu’ Syarh Al-Muhadzab” 1/105].
Perlu kita ingat bahwa hadits yang telah terbukukan dalam kitab-kitab hadits jumlahnya jauh di bawah jumlah hadits yang dikumpulkan dan dihafal oleh Al-Hafidz (minimal 100.000 hadits) dan jauh lebih kecil dari jumlah hadits yang dikumpulkan dan dihafal oleh Al-Hujjah (minimal 300.000 hadits). Sedangkan jumlah hadits yang dikumpulkan dan dihafal oleh Imam Mazhab yang empat, jumlahnya lebih besar dari jumlah hadits yang dikumpulkan dan dihafal oleh Al-Hujjah.
Asy-Syeikh Abu Amru mengatakan: ”Barang siapa menemui dari Syafi’i sebuah hadits yang bertentangan dengan mazhab beliau, jika engkau sudah mencapai derajat mujtahid mutlak, dalam bab, atau maslah itu, maka silahkan mengamalkan hal itu“.
Untuk itulah, kita mesti berhati-hati dan waspada terhadap propaganda yang dilontarkan sekelompok orang yang berteriak lantang “Kembali kepada al-Qur’an dan as-Sunnah” tanpa melalui ulama ahlussunnah wal jama’ah, yang senantiasa berusaha memaksakan pendapatnya agar mengikuti jalannya yang anti-taqlid dan anti-madzhab. Padahal mereka semua nyata-nyata hanya mau taqlid dan mengikuti apa yang dikatakan oleh syaikh-syaikh mereka yang mempunyai pandangan pemikiran yang sama dengannya.
Dengan demikian, janganlah kita beranjak satu langkah pun dari jalan yang dilalui oleh mayoritas umat Islam. Jadilah orang yang mendukung dan mempertahankannya dengan memerangi segala bentuk ekstremitas, yang terlalu kaku dan terlalu bebas. Peringatkan orang-orang untuk tidak fanatik terhadap madzhab-madzhab. Jelaskan bahwasanya sumber pertama (al-Qur’an) adalah segalanya, dengan catatan mampu mengerti dan memahaminya. Kita jangan sampai menjadi orang yang berlebih-lebihan dan melampaui batas. Sungguh itu musibah. Tiada daya dan upaya kecuali karena Allah, Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.
Wallahu A’lam Bishshowab.
(Zon Jonggol dengan beberapa perubahan/elhooda.net)
Sumber: ngaji.web.id
The post Nabi Tidak Memerintahkan Untuk Menginjak Kaki Temannya Saat Shalat Berjamaah appeared first on Ayo Baca.
Artikel ini hanyalah simpanan cache dari url asal penulis yang berkebarangkalian sudah terlalu lama atau sudah dibuang :
https://congkop.xyz/2020/12/29/nabi-tidak-memerintahkan-untuk-menginjak-kaki-temannya-saat-shalat-berjamaah/
 PING BABAB : Raksasa Aggregator Malaysia
PING BABAB : Raksasa Aggregator Malaysia