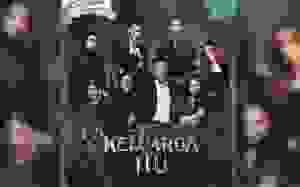Busking Zaman Ini Hanya Aktiviti Tiada Kaitan Dengan Keperitan Hidup

Dua minggu lepas saya dan isteri pergi makan malam di sebuah warung di pinggir Kuala Lumpur bersama kawan-kawan saya iaitu Seth, seorang jurugambar, penulis Hishamuddin Rais, dan seorang lagi kawan bernama Mus. Deretan jalan yang dipenuhi dengan warung masakan ala Pantai Timur itu cukup meriah ketika waktu makan malam. Kenderaan tidak berhenti keluar-masuk untuk singgah menjamu selera.
“Saya nak tanya abang satu soalan. Abang suka tak ‘buskers’ menyanyi kat sini?” tanya Seth kepada saya, merujuk kepada sekumpulan anak muda bermain muzik. Suara dan muzik yang mereka mainkan bergema dari speaker membuatkan saya berkerut.
Soalan Seth membuat saya serba-salah untuk menjawab. Gusar disalah tafsir. Saya mempunyai kawan yang mencari nafkah dengan menjadi pengamen. Pengamen istilah dalam bahasa indonesia merujuk kepada “busker”. Ia tidak semestinya menyanyi tetapi berbagai persembahan lain di tepi jalan seperti melukis potret atau karikatur, badut, silap mata, akrobatik, menari dan lain-lain. Di tempat kita lebih dikenali dengan gelaran seniman jalanan.
“Aku suka tonton ‘busker’ sejak zaman melepak di Central Market sekitar tiga puluh tahun dulu,” jawab saya. Saya memetik beberapa nama seniman jalanan yang saya minat seperti Adi Jagat, Sidek, dan Syed Amran. “Tetapi waktu itu mereka menyanyi dengan gitar sahaja tanpa ada mikrofon dan speaker. Mereka menyanyi sama ada lagu mereka sendiri atau pun “cover” lagu-lagu yang jarang kita dengar di radio. Selalunya berkisarkan hal masyarakat, politik, kritik sosial. Sebab itu aku suka,” jawab saya. Saya berasa sukar untuk bercakap kerana suara saya terpaksa melawan nyanyian ‘buskers’.
Seth, anak muda yang saya kenal sejak dia baru saja habis sekolah dan sudah menjadi bapa mengangguk dan memahami. Dia pun mengeluh kerana terganggu. Saya mengimbau zaman lebih awal kerancakan seniman jalanan di Kuala Lumpur. Ketika itu angkatan seniman 80-an sangat aktif mengamen di Central Market, di Jalan Masjid India, dan di pasar malam Jalan Tuanku Abdul Rahman. Acara ini masyhur dengan nama ‘baca sajak bawah tiang lampu’.
Nama-nama seperti Khalid Salleh, Sani Sudin, Pyanhabib, Ladin Nuawi, Kamarool Haji Yusof, atau juga Selamat Asrin sangat popular dan lantang mendeklamasikan sajak, melagukan puisi, dan berceloteh monolog. Saya masih belum melepak lagi waktu itu tetapi pernah jugalah sekali dua menyaksikan persembahan mereka. Masa lapang saya selepas habis bekerja terisi oleh mereka. Jiwa saya kenyang dek puisi-puisi mereka. Lagu-lagu rakyat yang didendangkan oleh seniman jalanan ini seperti meraikan saya – seorang mekanik yang bekerja di sebuah bengkel memasang dan membaiki kenderaan.
“Kegiatan seniman jalanan di Kuala Lumpur zaman itu ada dirakamkan dalam dua filem arahan seniman Nasir Jani iaitu Kembara Seniman Jalanan dan Rozana Cinta ’87. Suasana ini sudah tidak ada lagi,” kata saya.
Saya masih lagi setia melepak di Central Market pada awal 90-an yang mana ketika itu muncul nama-nama lain menyanyi di situ seperti Sherry, Meor, Nik Jidan, Nan Blues, dan seorang dua lagi. Ketika itu saya sudah pun masuk belajar di sebuah maktab perguruan di ibu kota. Selepas habis kuliah, saya seorang diri tanpa ditemani kawan-kawan dari maktab akan menaiki bas mini menuju ke Central Market. Saya ketagih persembahan seniman-seniman jalanan ini. Uniknya ketika itu ada juga band rock siap berpakaian macam band rock popular bermain muzik menyanyikan lagu-lagu ‘cover’ sehingga penonton memenuhi jalan. Tahukah anda persembahan mereka itu hanyalah penyeri sahaja kerana mereka sebenarnya jual bedak sejuk! Saya tidak pasti berapa botol bedak sejuk terjual tetapi setiap kali mereka ada, penonton amat ramai. Maklumlah menonton ‘konsert rock’ percuma.
“Jadi, sebenarnya abang suka atau tidak ‘buskers’ yang bising dan menyanyikan lagu ‘cover’?” tanya Seth.
Saya masih sangsi hendak menjawab. Apakah saya sendiri terkeliru? Saya akui saya akan duduk ternganga jika persembahan seseorang itu unik seperti menyanyikan lagu ciptaan sendiri dengan senikata yang luar dari kebiasaan, iaitu bukan lagu kisah kecewa putus cinta. Tetapi jika konsep sebegitu dinyanyikan dengan kuat menggunakan speaker, apakah telinga saya boleh terima? Terganggukah selera makan saya?
Di kota Paris, di San Francisco, di Madrid, atau di Barcelona, saya dan isteri seronok duduk menyaksikan persembahan pengamen yang bervariasi. Kreativiti mereka berbagai. Puas! Semasa tinggal di Jakarta saya berkawan dengan Titi Joe dan Ragil, dua cewek yang sepenuh masa mengamen. Mereka menghiburkan orang ramai kerana tuntutan hidup. Menyanyi tepi jalan, dalam bas, di warung-warung demi menyara hidup. Mereka meninggalkan kampung, bergelandangan di kota yang sibuk.
Bertahun mereka tidur di bawah jambatan. Kisah Titi Joe sebagai pengamen anda boleh lihat di YouTube, sebuah dokumentari bertajuk Jalanan, arahan Daniel Ziv. Dalam filem tersebut dipaparkan kecekalan mereka mengharung cabaran menyanyi untuk mengisi perut di kota besar yang sesak dan padat. Sebab itu barangkali lagu-lagu yang mereka dendangkan ‘kena’ dan ‘melekat’. Lagu dendangan mereka dan kisah peribadi tentang perlawanan hidup mereka seiring. Kita barangkali tidak macam itu. Kita menyanyikan lagu perjuangan tetapi masih boleh minum kopi mahal. Ia tak selari. Jadi, rohnya tak ada. Hambar. Tak sampai. Agaknyalah, itu yang saya rasa.
“Buskers” zaman ini tidak ada perlawanan seperti itu. Mereka ada kerja lain mungkin. “Busking” hanya aktiviti. Tiada kaitan dengan keperitan hidup.
Namun, itulah evolusi suasana seniman jalanan di Kuala Lumpur hari ini agaknya. Penggiatnya bernyanyi untuk menghibur, suka-suka, santai sahaja di samping mencari wang. Ketika zaman ‘kutu 80-an’, mungkin acara baca sajak tepi jalan begitu juga, suka-suka; Buku-buku sajak terbitan mereka sendiri yang dijual oleh mereka sekadar untuk bayar teh tarik dengan kawan-kawan tetapi mereka mengisi persembahan dengan membawa suara rakyat. Ada ‘benda’ yang mereka suarakan.
Boleh atau tidak “buskers” menyanyi kuat menggunakan speaker? Soalan Seth masih lagi saya tidak jawab. Cuma saya masih ingat ketika zaman seniman Adi Jagat dan Sidek berpadu menghibur khalayak di sebatang jalan luar Central Market, mereka terganggu dengan persembahan seorang lagi “busker” di pangkal jalan yang sama – bernyanyi menggunakan “minus one” dengan sistem bunyi yang kuat. Saya masih ingat kedua mereka beraksi gila-gila, menyanyi kuat-kuat seperti menyindir dan memprotes. Suara mereka tenggelam ditelan sistem bunyi yang di sebelah sana. Mereka sama-sama “busker” tetapi mereka juga tidak suka. Ketenteraman mereka juga terganggu. Mereka tidak dapat menumpukan perhatian pada persembahan mereka. Maknanya, kalau bising ia mengganggu.
Tetapi kisah ini tidak terlintas di kepala saya sewaktu Seth bertanya. Saya cuma menjawab, “kalau setakat nak dengar ‘cover version’ lebih baik aku dengar yang ‘original’.”
“Aduh! Bisanya ‘statement’ abang,” jawab Seth, sambil memerhatikan isteri saya, Mus, dan Hishamuddin Rais yang sibuk menikmati hidangan tanpa pedulikan perbualan kami. Mungkin juga muzik latar terlalu kuat sehingga mereka tidak dapat mendengar dengan jelas butir perbincangan kami. Jadi, mereka malas masuk campur dan meneruskan makan lebih baik.
Untuk isu ini, saya ingin meminta maaf kepada “buskers” era ini. Saya rasa saya yang salah dalam hal ini. Apa yang diomelkan ini hanya pandangan peribadi saya dan pandangan saya ini datangnya dari pengalaman serta pemerhatian saya yang sudah ketinggalan zaman agaknya. Pastinya ketika saya sudah tidak suka makan di tempat sebegitu masih ramai lagi yang menyukai anda. Orang hanya mahu santai-santai, saya pula yang terlalu serius. Ya! Zaman sudah berubah, cuma saya yang tidak betah! - FMT
Artikel ini adalah pandangan penulis dan tidak semestinya mewakili MMKtT.
Artikel ini hanyalah simpanan cache dari url asal penulis yang berkebarangkalian sudah terlalu lama atau sudah dibuang :
http://malaysiansmustknowthetruth.blogspot.com/2023/02/busking-zaman-ini-hanya-aktiviti-tiada.html
 PING BABAB : Raksasa Aggregator Malaysia
PING BABAB : Raksasa Aggregator Malaysia